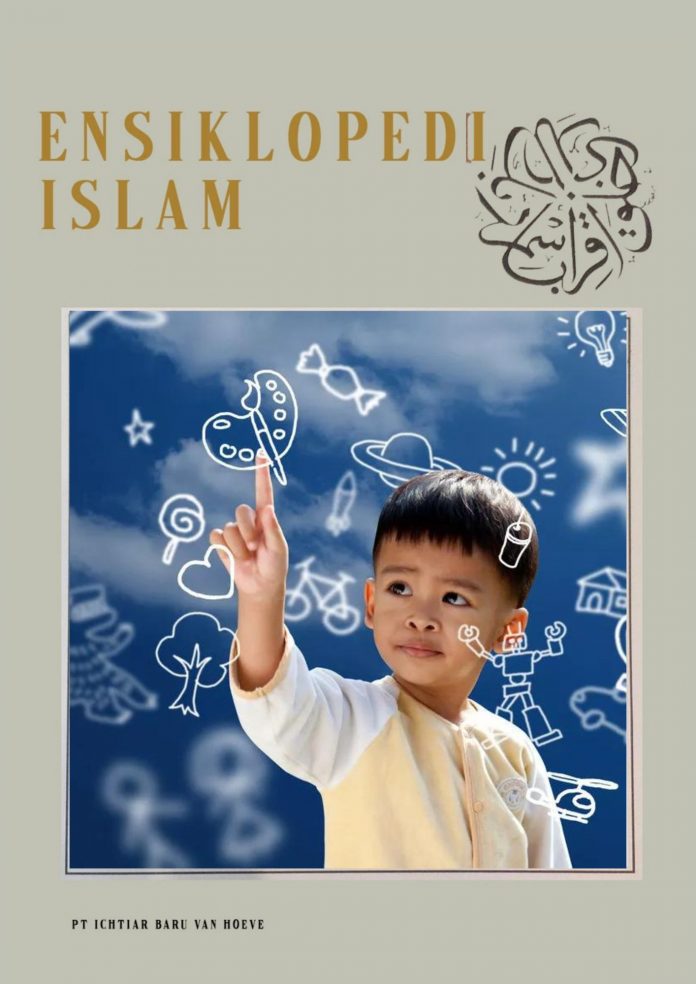Zihni berarti pemahaman (al-fahm) dan daya pikir (al-‘aql).
Zihni merupakan daya (kekuatan) yang terdapat pada akal manusia yang menyebabkannya dapat menyusun konsep mengenai suatu hal sehingga dapat membedakan yang baik dan buruk, salah dan benar.
Zihni terdiri dari:
(1) al-Hiss al-musytarak (indra bersama), yaitu menerima segala yang ditangkap pancaindra;
(2) al-quwwah al-khayal (daya khayal), yaitu menyimpan segala yang diterima indra bersama;
(3) al-quwwah al-mutakhayyilah (daya renung), yaitu menyusun segala hal yang disimpan daya khayal;
(4) al-quwwah al-wahmiyyah (daya kira), yaitu menangkap hal abstrak yang terlepas dari materinya; dan
(5) al-quwwah al-hafizah (daya simpan), yaitu daya yang dapat menyimpan hal abstrak yang diterima daya kira.
Di kalangan filsuf modern, dzihni diartikan sebagai daya tangkap dan daya pikir, sebagai lawan dari pancaindra. Zihni adalah kemampuan seseorang untuk berpikir dan memahami masalah.
Zihni sering pula disebut akal atau jiwa, yakni jiwa yang memiliki daya sebagaimana tersebut di atas. Ada pula yang membedakan antara zihni dan akal. Menurut pendapat ini, akal digunakan untuk menangkap persoalan yang bersifat kekal dan mutlak, sedangkan dzihni digunakan untuk menangkap persoalan yang bersifat at-tajribiyyah (latihan atau coba-coba) dan berubah sesuai dengan perubahan gambaran yang dihasilkan pancaindra.
Zihni baru dapat menarik suatu kesimpulan apabila didahului mukadimah (pendahuluan) dan fardiyyah (perincian, satuan). Adapun akal bersifat hadasi (kekuatan luar biasa) yang dapat menarik kesimpulan tanpa didahului mukadimah dan fardiyyah.
Perbedaan antara dzihni dan akal selanjutnya dikemukakan Plato (427–347 SM, filsuf Yunani). Menurutnya, hadasi adalah daya yang dapat menjangkau masalah yang lebih tinggi, sedangkan akal adalah daya yang dapat menjangkau masalah yang lebih rendah, yaitu masalah yang harus didahului mukadimah dan fardiyyah.
Sebaliknya, ada yang berpendapat bahwa hadasi lebih rendah dari akal karena hadasi hanya dapat menangkap hal yang datang dari luar melalui pancaindra, sedangkan akal dapat menangkap masalah yang lebih tinggi, yaitu masalah ilahiah (ketuhanan).
Ibrahim Madkur, pakar filsafat Islam dari Mesir, termasuk yang mendukung adanya dzihni sebagai daya yang lebih tinggi dari pancaindra. Menurutnya, dzihni dapat memahami sesuatu secara langsung tanpa melalui perantara, sedangkan pancaindra dapat memperoleh gambaran mengenai sesuatu apabila ada masukan dari luar.
Namun, apa yang ada dalam dzihni (pemikiran) tersebut tidak selamanya dapat dicontohkan dalam kenyataan. Ia terkadang hanya ada dalam pemikiran, tetapi tidak ada dalam kenyataan.
Hasil kerja dzihni adalah al-burhan, yaitu pengetahuan yang didasarkan pada dalil kuat yang dapat dilihat dalam kenyataan. Apa yang dihasilkan dzihni berjalan sesuai dengan cara bergeraknya pemikiran untuk sampai kepada tujuan yang memerlukan lafal (simbol) atau rumus tertentu, yang kemudian dikembangkan dalam ilmu mantik (logika).
Untuk mencapai pemikiran tersebut diperlukan perantara yang dapat mengalihkan bagian juz’i (satuan) kepada bagian kulli (menyeluruh) atau sebaliknya, sehingga dapat dihasilkan kaidah atau prinsip mengenai sesuatu, yang selanjutnya dapat menghasilkan suatu teori.
Zihni dalam kajian filsafat merupakan alat untuk menghasilkan konsep atau rumus dengan menggunakan langkah tertentu secara teratur sebagaimana diatur dalam ilmu mantik atau filsafat ilmu.
Dari pembahasan dzihni muncul sistem berpikir yang dikenal dengan istilah logico hypothetico verifikasi yang langkahnya sebagai berikut.
(1) Perumusan masalah, yaitu pernyataan tentang objek empiris yang jelas batasnya dan faktor yang terkait di dalamnya. A
(2) Penyusunan kerangka berpikir, yaitu argumen yang menjelaskan hubungan yang mungkin terdapat antara berbagai faktor dan membentuk konstelasi permasalahan. Kerangka berpikir disusun secara rasional berdasarkan premis ilmiah yang telah teruji kebenarannya dengan memperhatikan faktor empiris yang relevan dengan permasalahan.
(3) Perumusan hipotesa, yaitu jawaban sementara atas pertanyaan yang diajukan yang materinya merupakan kesimpulan dari kerangka berpikir yang dikembangkan.
(4) Pengujian hipotesa, yaitu pengumpulan fakta yang relevan dengan hipotesa yang diajukan untuk memperlihatkan apakah terdapat fakta yang mendukung hipotesa tersebut atau tidak.
(5) Penarikan kesimpulan, yaitu penilaian apakah hipotesa yang diajukan ditolak atau diterima.
Sekiranya dalam proses pengujian tersebut terdapat fakta yang cukup untuk mendukung hipotesa, hipotesa tersebut diterima atau sebaliknya.
Hipotesa yang diterima itu kemudian dianggap menjadi bagian dari pengetahuan ilmiah sebab telah memenuhi persyaratan keilmuan yang mempunyai Patung pemikir karya Auguste Rodin (1840–1917), pematung Perancis kerangka penjelasanyang konsisten dengan pengetahuan ilmiah dan telah terwujud kebenarannya.
Pengertian kebenaran di sini harus ditafsirkan secara pragmatis. Artinya, sampai pada saat ini belum terdapat fakta yang menyatakan sebaliknya.
Hasil pemikiran dzihni dalam kegiatan ilmiah disebut hikmah an-nazariyyah (pengetahuan tingkat tinggi yang diperoleh melalui perenungan) yang dibagi menjadi tiga bagian:
(1) hikmah an-nazariyyah, yang berhubungan dengan sesuatu yang bergerak dan berubah yang kemudian dinamakan hikmah tabi‘iyyah, yaitu pengetahuan mengenai sesuatu yang tampak di alam nyata;
(2) dzihni, yang berhubungan dengan sesuatu yang bersifat pemikiran dan tidak berhubungan dengan sesuatu yang bergerak, walaupun dalam wujudnya bercampur dengan sesuatu yang berubah; pengetahuan seperti ini disebut hikmah riyadiyyah; dan
(3) al-falsafah al-ilahiyyah (filsafat ketuhanan), yaitu hikmah yang berhubungan dengan sesuatu yang wujudnya tidak memerlukan percampuran dengan sesuatu yang berubah. Ia sedikit pun tidak terpengaruh oleh yang berubah itu.
Sekalipun lahiriahnya bercampur, zatnya tidak bercampur. Al-Falsafah al-ilahiyyah merupakan suatu cara yang dapat digunakan untuk mengenal hal yang berhubungan dengan ketuhanan.
Berpikir merupakan proses memahami realitas dan penilaian kritis terhadap pemahaman itu. Penilaian kritis tersebut merupakan upaya menggugat keabsahan pemahaman dengan harapan upaya realisasinya dapat dipertanggungjawabkan.
Dalam penilaian kritis diperlukan kejujuran intelektual, karena sering terjadi pemahaman manusia terhadap realitas merupakan opini yang dipengaruhi kepentingan tertentu yang secara moral tidak dapat dipertanggungjawabkan.
Opini bukanlah fakta, bahkan sering terjadi opini tentang fakta ternyata berbeda dengan faktanya sendiri. Orang tertarik karena opini, bukan karena faktanya, sehingga tidak terjadi perubahan apa-apa terhadap fakta meskipun fakta itu memerlukan perubahan.
Berpikir merupakan kegiatan yang sepenuhnya bebas. Kotak pemikiran terjadi karena kotak budaya, terutama yang terjadi dalam proses pendidikan. Kegiatan berpikir merupakan kegiatan otonom, bahkan berada di luar penilaian etik.
Orang boleh saja berpikir melalui dzihninya tentang perampokan, tetapi ia sendiri tidak pernah melakukan perbuatan terlarang itu dan tidak dapat dituntut secara hukum di pengadilan.
Demikian pula berpikir tentang kebebasan bukan berarti pembebasan manusia dari segala ikatan atau norma hukum tertentu. Jika ada yang mengikat hal berpikir, mungkin itu adalah hukum berpikir dalam pengertian metodologis dan objek yang dipikirkannya.
Daftar Pustaka
Abu Rayyan, Muhammad Ali. Qira’at fi al-Falsafah. Iskandariyah: Dar al-Qaumiyyah, 1967.
al-Ahwani, Ahmad Fu’ad. Ahwal an-Nafs fi an-Nafs wa Baqa’uha wa Maudu‘uha li asy-Syaikh ar-Ra’is Ibn Sina. Cairo: Isa al-Babi al-Halabi wa Syuraka’uh, 1952.
Ibnu Sina. asy-Syifa’ (al-Mantiq). Cairo: al-Hai’ah al-‘Ammah li asy-Syu’un al-Mat-abi‘i al-‘Amiriyat, 1964.
al-Marbawi, Abdurra’uf. Qamus al-Marbawi. Cairo: Mustafa al-Babi al-Halabi, t.t.
Qasim, Mahmud. Dirasah fi al-Falsafah al-Islamiyyah. Cairo: Dar al-Fikr, 1970.
Suriasumantri, Jujun S. Filsafat Ilmu Sebuah Pengantar Populer. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1988.
Wehr, Hans. A Dictionary of Modern Written Arabic. Beirut: Librairie Du Liban & London: Macdonald & Evans Ltd., 1974.
Abuddin Nata