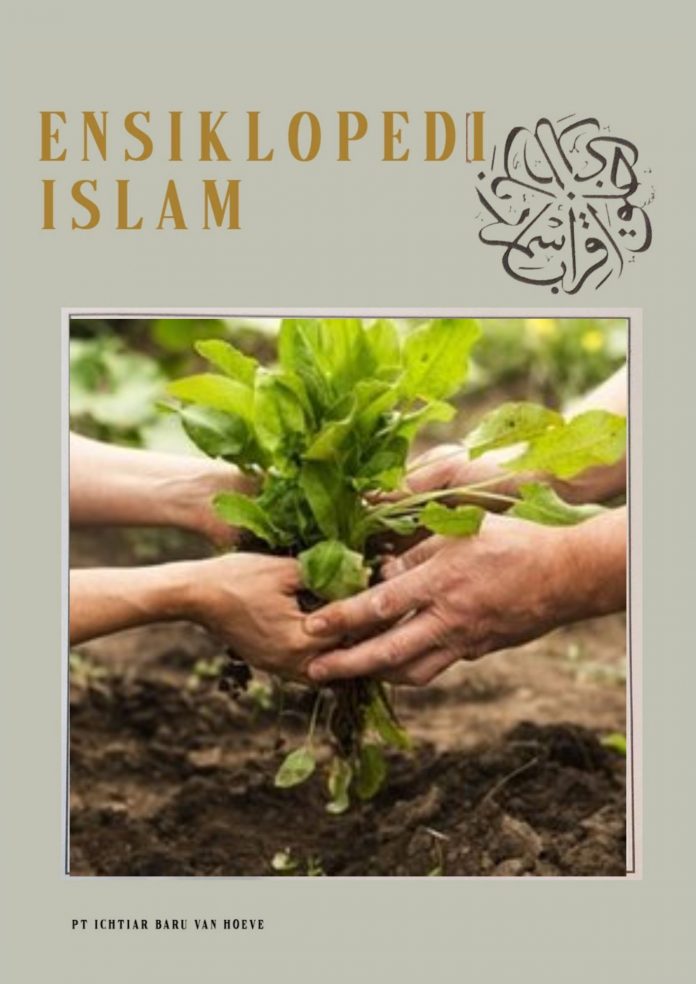Dari segi bahasa, wada‘a berarti “meninggalkan” atau “berpisah”. Menurut istilah, wada‘a berarti “sesuatu yang ditempatkan bukan pada pemiliknya untuk dipelihara”. Di Indonesia, wadi‘ah diterjemahkan dengan “titipan”. Bahasan wadi‘ah dalam fikih termasuk ke dalam salah satu bentuk muamalah tolong-menolong antarmanusia.
Menurut Mazhab Hanafi, wadi‘ah adalah mengikut sertakan orang lain dalam memelihara harta. Adapun menurut Mazhab Syafi‘i dan Mazhab Maliki, wadi‘ah adalah mewakilkan orang lain untuk memelihara harta tertentu dengan cara tertentu.
Wadi‘ah sebagai salah satu akad dalam rangka tolong-menolong sesama manusia disyariatkan dalam surah an-Nisa’ (4) ayat 58,
“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanah kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil.”
Ayat di atas menurut para mufasir berkaitan dengan penitipan kunci Ka‘bah sebagai amanah Allah SWT kepada Usman bin Talhah, seorang sahabat. Dan dalam surah al-Baqarah (2) ayat 283 Allah SWT berfirman,
“…Akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanahnya (utangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah tuhannya, dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian…”
Selain itu Rasulullah SAW bersabda dalam sebuah hadis,
“Serahkanlah amanah orang yang mempercayai engkau dan jangan kamu mengkhianati orang yang mengkhianati engkau” (HR. Abu Dawud, at-Tirmizi, dan al-Hakim).
Berdasarkan ayat dan hadis ini, ulama sepakat bahwa akad wadi‘ah (titipan) itu hukumnya boleh dan mandub (dibolehkan) dalam rangka saling tolong-menolong sesama manusia. Oleh sebab itu, Ibnu Qudamah (ahli fikih Mazhab Hanbali), menyatakan bahwa sejak zaman Rasulullah SAW dan generasi berikutnya, wadi‘ah telah menjadi ijma‘ ‘amali (konsensus dalam praktek) bagi umat Islam dan tidak ada seorang ulama pun yang mengingkarinya.
Sebagai sebuah akad, ketentuan sah atau tidaknya wadi‘ah tergantung pada syarat dan rukunnya. Syarat wadi‘ah ada dua macam, yaitu: 1) orang yang berakad itu telah akil balig, dan 2) barang titipan itu berbentuk materi yang bisa dipegang/dikuasai.
Menurut Mazhab Hanafi, rukun wadi‘ah hanya ijab (pernyataan menitipkan barang kepada seseorang) dan kabul (pernyataan menerima titipan itu dari orang yang menitipkan barang). Adapun rukun wadi‘ah bagi jumhur ulama adalah:
1) dua orang yang berakad,
2) sesuatu yang dititipkan, dan
3) akad penitipan.
Akad wadi‘ah mengikat kedua belah pihak. Pihak yang dititipi bertanggung jawab memelihara wadi‘ah sebagai amanah. Ia tidak boleh meminta upah atas jasanya memeli hara barang itu.
Ulama berbeda pendapat tentang cara memelihara wadi‘ah. Ulama Mazhab Hanafi dan Mazhab Hanbali mengatakan bahwa wadi‘ah harus dipelihara oleh orang yang dititipi atau oleh orang yang berada di bawah tanggung jawabnya (keluarganya). Menurut Mazhab Hanafi, wadi‘ah juga menjadi tanggung jawab orang yang bekerja sama dengan orang yang dititipi, seperti mitra dagangnya atau karyawannya di kantor.
Mazhab Maliki mengatakan, pihak keluarga yang ikut bertanggung jawab atas barang titipan itu hanya orang yang dapat dipercayai oleh orang yang dititipi seperti istri, anak atau pembantunya. Mazhab Syafi‘i lebih ketat mengatakan wadi‘ah itu hanya boleh dipelihara oleh orang yang dititipi (yang berakad).
Persoalan lain yang terkait dengan wadi‘ah adalah apa kah akad ini bersifat amanah atau mazmunah (mempunyai risiko ganti rugi). Jika bersifat amanah, apabila terjadi keru sakan atau kehilangan tanpa kelalaian dan unsur kesengajaan, pihak yang dititipi tidak dapat dituntut ganti rugi. Akan tetapi jika bersifat mazmunah, segala kerusakan atau kehilangan harus diganti oleh orang yang dititipi.
Ulama sepakat bahwa akad wadi‘ah hanyalah akad amanah dengan imbalan pahala dari Allah SWT. Jika barang itu hilang atau rusak tanpa unsur kesengajaan, pihak yang dititipi tidak dapat dituntut ganti rugi. Hal ini didasarkan pada sabda Rasulullah SAW: “Orang yang dipercayai memegang amanah/titipan tidak bisa dituntut ganti rugi” (HR. Daruqutni dan al-Baihaqi dari Amr bin Syu‘aib).
Akan tetapi, wadi‘ah sebagai akad yang bersifat amanah bisa berubah menjadi akad yang bersifat mazmunah dengan syarat sebagai berikut.
1) Orang yang dititipi tidak memelihara barang titipan itu.
2) Barang titipan itu dititipkan lagi kepada orang lain yang bukan keluarga dekat dan di bawah tanggung jawabnya.
3) Barang titipan itu dimanfaatkan oleh orang yang dititipi.
4) Barang titipan itu dibawa oleh orang yang dititipi ketika ia melakukan perjalanan yang memakan waktu dan biaya (musafir).
5) Orang yang dititipi mengingkari adanya barang titipan ketika orang yang menitipkan meminta kembali barang itu.
6) Orang yang dititipi mencampur barang itu dengan harta pribadinya, sehingga sulit untuk dipisahkan.
7) Orang yang dititipi melanggar syarat yang telah ditentukan.
Dalam perkembangannya bentuk titipan di dunia Islam menjadi semakin bervariasi dan pihak yang terlibat pun semakin beragam. Umpamanya giro pos dan tabungan yang dikelola oleh perbankan pada dasarnya merupakan uang titipan. Akan tetapi, tabungan uang dalam bank terkait dengan masalah bunga bank, sedangkan wadi‘ah hanya merupakan akad tolong-menolong tanpa adanya imbalan jasa.
Di samping itu, uang yang dititipkan dipergunakan bank sehingga ia mendapatkan keuntungan. Keuntungan ini dibagikan kepada para nasabah sesuai dengan peraturan bank. Kemudian, biaya administrasi untuk uang di bank harus dikeluarkan oleh pihak yang menitipkan uang, sebagai imbalan jasa yang diberikan bank.
Jika uang titipan itu dimanfaatkan pihak bank, kemudian dikembalikan lagi secara utuh, dan bahkan dilebihkan sebagai imbalan jasa, menurut Mazhab Maliki dan Mazhab Hanafi, hukumnya boleh. Tetapi menurut Mazhab Syafi‘i, tidak boleh dan akadnya dinyatakan gugur. Tentang imbalan jasa (keuntungan) tersebut terdapat tiga pendapat. 1) Keuntungan menjadi milik orang yang dititipi (dalam kasus ini pihak bank). 2) Keuntungan menjadi milik baitulmal (perbendaharaan negara). 3) Keuntungan untuk pemilik uang.
Daftar Pustaka
Ibnu Qudamah. al-Mugni. Riyadh: Maktabah ar-Riyadh al-Hadisah, 1981.
Ibnu Rusyd. Bidayah al-Mujtahid wa Nihayah al-Muqtasid. Cairo: al-Babi al-Halabi, 1960.
al-Jaziri, Abdurrahman. al-Fiqh ‘ala al-Madzahib al-Arba‘ah. Beirut: Dar al-Fikr, 1986.
al-Kasani. Bada’i‘ as-sana’i‘. Beirut: Dar al-Fikr, 1982.
Sabiq, Sayid. Fiqh as-Sunnah. Beirut: Dar al-Fikr, 1986.
as-San‘ani, Muhammad bin Ismail al-Kahlani. Subul as-SalÎm. Kuwait: Dar as-Salafiyyah, 1985.
az-Zuhaili, Wahbah. al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh. Beirut: Dar al-Fikr, 1984.
Nasrun Haroen