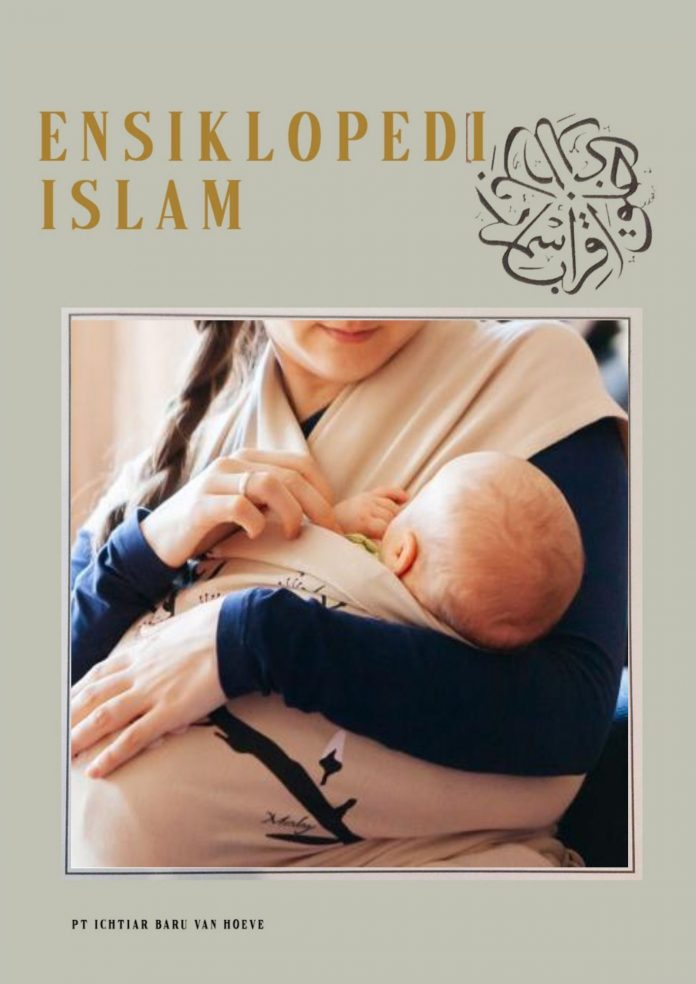Masuknya air susu manusia ke dalam perut seorang anak yang umurnya tidak lebih dari 2 tahun disebut radaah. Ulama fikih memberikan batasan usia 2 tahun karena sampai usia tersebut perkembangan biologis anak sangat ditentukan kadar susu yang diterimanya.
Dalam fikih Islam, persoalan radaah mempunyai dampak terhadap sah atau tidaknya suatu pernikahan. Apabila seorang lelaki ketika kecil menyusu kepada seorang perempuan (bukan ibu atau orang yang haram dikawininya), ia diharamkan kawin dengan ibu tempat ia menyusu tersebut serta seluruh perempuan yang mempunyai nasab dengan ibu susuan itu, baik secara vertikal maupun horizontal. Alasannya adalah firman Allah SWT yang berarti:
“Diharamkan atas kamu (mengawini) ibu-ibumu, anak-anakmu yang perempuan, saudara-saudaramu yang perempuan, saudara-saudara bapakmu yang perempuan, saudara-saudara ibumu yang peremp-uan, anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki, anak perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan, ibu-ibumu yang menyusui kamu, saudara perempuan sepersusuan…” (QS.4:23).
Sekalipun ayat di atas hanya menyebutkan perempuan yang diharamkan karena susuan itu adalah ibu susuan dan saudara-saudara perempuan sepersusuan, ulama fikih menyatakan bahwa yang diharamkan itu tidak terbatas pada dua pihak itu saja.
Dalam hal ibu susuan dan saudara perempuan sepersusuan tersebut berlaku hukum sebagaimana halnya ibu dan saudara perempuan kandung. Di pihak ibu kandung, yang termasuk haram dikawini seorang pria adalah (1) ke atas: nenek dan seterusnya, (2) ke bawah: anak perempuan dan seterusnya, dan (3) ke samping: saudara perempuan.
Pemberlakuan hukum haram mengawini perempuan dari pihak ibu susuan dan perempuan sepersusuan di atas didasarkan pada teori kias (analogi). Dalam sebuah hadis diriwayatkan bahwa Rasulullah SAW diminta mengawini anak Hamzah. Lalu Rasulullah SAW menjawab, “Sesungguhnya ia tidak halal bagiku, karena ia adalah anak saudara sesusuku, dan apa-apa yang diharamkan karena nasab (keturunan) diharamkan juga karena susuan” (HR. Bukhari dan Muslim dari Ibnu Abbas).
Sekalipun ulama fikih telah sepakat menyatakan keharaman menikahi ibu susuan dan seluruh wanita yang seketurunan, terjadi perbedaan pendapat di kalangan mereka dalam menentukan kadar susuan yang mengharamkan nikah itu, umur anak yang disusui, dan urgensi saksi dalam masalah radaah.
Di kalangan ahli fikih terdapat tiga pendapat mengenai kadar susuan yang mengharamkan nikah. Pendapat pertama dikemukakan Daud az-Zahiri (202 H/815 M–270 H/884 M). Menurutnya, kadar susuan yang mengharamkan nikah itu minimal tiga kali hisap.
Alasan yang dikemukakan adalah sabda Rasulullah SAW yang menyatakan: “Satu dan dua kali hisap tidak mengharamkan” (HR. Ahmad bin Hanbal, Muslim, an-Nasa’i, at-Tirmizi, dan Ibnu Majah dari Aisyah; hadis yang senada juga datang melalui jalur Abdullah bin Zubair dan Ummu Fadl). Menurut Daud az-Zahiri, hukum susuan yang ditentukan secara umum oleh ayat Al-Qur’an di atas dibatasi oleh hadis ini.
Pendapat kedua dikemukakan ulama Mazhab Syafi‘i dan Hanbali. Menurut mereka, kadar susuan yang mengharamkan nikah adalah lima kali susuan atau lebih dan dilakukan secara terpisah-pisah. Alasan mereka didasarkan pada hadis Rasulullah SAW dari Aisyah yang menyatakan:
“Ayat Al-Qur’an pernah turun dalam mengharamkan wanita tempat menyusu jika susuan itu sepuluh kali susuan. Kemudian hukum itu dinasakhkan (dibatalkan) menjadi lima kali susuan. Kemudian setelah Rasulullah wafat, hukum lima kali susuan itu tetap berlaku” (HR. Muslim, Abu Dawud, dan an-Nasa’i).
Hadis lain dari Aisyah menyatakan bahwa Nabi SAW bersabda, “Susuilah ia (anak kecil) sebanyak lima kali susuan, maka ia akan menjadi anak karena susuan” (HR. Malik dan Ahmad bin Hanbal).
Pendapat ketiga dianut ulama Mazhab Hanafi dan Maliki. Menurut mereka, susuan yang mengharamkan itu tidak dibatasi kadarnya, sesuai dengan umumnya pengertian surah an-Nisa’ (4) ayat 23 di atas. Menurut mereka, yang penting air susu yang dihisap itu sampai ke perut anak sehingga memberikan energi dalam pertumbuhan anak. Selain ayat di atas, pendapat mereka didasari pula oleh riwayat dari Uqbah bin Haris yang menyatakan:
“Aku pernah kawin dengan Ummu Yahya binti Ihab. Kemudian datang seorang budak perempuan hitam seraya berkata, ‘Aku pernah menyusui kamu berdua’. Kasus ini saya ceritakan kepada Nabi SAW. Kemudian Nabi SAW bersabda, ‘Bagaimana lagi? Ceraikan ia’.” (HR. Bukhari dan Muslim).
Dalam hadis ini Rasulullah SAW tidak mempertanyakan berapa kali perempuan itu menyusui Uqbah dan Ummu Yahya. Kalau memang kadar susuan menjadi ukuran haramnya nikah, tentu Nabi SAW akan bertanya lebih lanjut sehingga jelas kadar air susu yang dimaksud.
Menurut ulama Mazhab Hanafi dan Maliki, hadis-hadis yang mencantumkan kadar susuan tiga atau lima kali tidak dapat dijadikan landasan hukum, bukan saja karena terjadinya perbedaan bilangan susuan dalam masing-masing hadis, tetapi karena bilangan itu tidak dijumpai dalam Al-Qur’an.
Ulama fikih mensyaratkan susuan yang mengharamkan itu sebagai berikut:
1) Air susu itu berasal dari susu wanita tertentu (jelas identitasnya), baik telah atau sedang bersuami.
2) Air susu itu masuk kerongkongan anak, baik melalui isapan langsung pada puting payudara wanita itu maupun melalui alat penampung susu, seperti gelas, botol, dan lain-lain.
3) Penyusuan itu dilakukan melalui mulut atau hidung
anak (infus) yang disusui. Ulama Mazhab Hanafi, Mazhab Syafi‘i, dan Mazhab Hanbali mengatakan apabila susu itu dialirkan melalui alat injeksi, bukan melalui mulut atau hidung, maka tidak mengharamkan nikah antara wanita pemilik susu dan atau keturunannya. Adapun menurut ulama Mazhab Maliki, dengan cara ini pun tetap haram.
4) Menurut ulama Mazhab Hanafi dan Mazhab Maliki air susu itu harus murni, tidak bercampur dengan yang lainnya. Apabila susu itu bercampur dengan cairan lainnya, maka menurut mereka, diteliti mana yang lebih dominan. Apabila yang dominan adalah susu, maka bisa mengharamkan nikah.
Apabila yang dominan adalah cairan lain itu, maka tidak mengharamkan nikah. Akan tetapi, ulama Mazhab Syafi‘i dan Mazhab Hanbali menganggap susu yang dicampur dengan cairan lain itu pun sama saja hukumnya dengan susu murni dan tetap mengharamkan nikah.
Apabila susu itu dicampur dengan susu wanita lain, menurut Imam Abu Hanifah dan sahabatnya, Imam Abu Yusuf, yang haram dinikahi adalah wanita yang air susunya lebih banyak dalam campuran itu. Akan tetapi, menurut jumhur ulama, termasuk Muhammad bin Hasan asy-Syaibani dan Zufar bin Hudail bin Qais al-Kufi (110 H/728 M–158 H/775 M) (keduanya ahli fikih Mazhab Hanafi) seluruh pemilik susu yang dicampur itu haram dinikahi anak tersebut, baik jumlah susu mereka sama atau salah
satunya lebih banyak.
5) Menurut mazhab fikih yang empat (Mazhab Hanafi, Mazhab Maliki, Mazhab Syafi‘i, dan Mazhab Hanbali), susuan itu harus dilakukan pada usia anak sedang menyusu. Berkenaan dengan usia anak susuan, ulama sepakat menyatakan bahwa umur anak kecil yang menyusui itu tidak lebih dari 2 tahun.
Hal ini didasarkan pada firman Allah SWT dalam surah al-Baqarah (2) ayat 233 yang berarti: “Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan.” Dalam sebuah riwayat dikatakan: “Tidak ada penyusuan kecuali dalam batas umur dua tahun” (HR. Daruqutni dari Ibnu Abbas).
Jika anak sudah besar (di atas umur 2 tahun), timbul perbedaan pendapat di kalangan ulama fikih tentang apakah susuan tersebut mengharamkan ia menikah dengan ibu susuan dan perempuan sepersusuannya.
Menurut jumhur ulama, susuan tersebut tidak mengharamkan nikah. Alasan yang mereka kemukakan adalah surah al-Baqarah (2) ayat 233 di atas yang menyatakan bahwa umur 2 tahun merupakan kesempurnaan suatu susuan, dan hadis Rasulullah SAW yang menyatakan bahwa susuan yang mengharamkan itu adalah susuan yang dapat menguatkan tulang dan menumbuhkan daging (HR. Abu Dawud dari Ibnu Mas‘ud).
Menurut jumhur ulama, air susu yang diminum anak yang sudah besar tidak akan menguatkan tulang dan menumbuhkan daging, karena makanan mereka sudah bervariasi. Akan tetapi ulama Mazhab az-Zahiri menyatakan bahwa radaah tersebut menyebabkan haramnya nikah antara anak dan ibu susuan dan saudara sepersusuannya. Alasan mereka juga didasarkan pada ayat Al-Qur’an yang sama.
Persoalan lain yang dikemukakan ulama dalam kaitannya dengan susuan yang mengharamkan ini adalah persoalan saksi dalam radaah itu. Ulama sepakat menyatakan bahwa saksi itu penting, karena sering terjadi wanita dengan laki-laki yang sesusuan tidak saling mengenal.
Namun menjadi perdebatan apakah saksi itu cukup satu atau harus dua orang. Imam Hanbali menyatakan saksi itu boleh satu orang saja, dan boleh juga seorang perempuan, sebagaimana kasus Uqbah bin Haris dengan Ummu Yahya yang dikemukakan di atas. Akan tetapi ulama Mazhab Hanafi menyatakan bahwa kesaksian dalam masalah susuan sama saja dengan kesaksian dalam masalah lain, yaitu harus dua orang laki-laki atau satu orang laki-laki dan dua orang perempuan.
Jika persaksian itu hanya dikemukakan oleh satu orang saja, ini berarti ia menyaksikan untuk dirinya sendiri. Alasan yang dikemukakan ulama Mazhab Hanafi adalah firman Allah SWT dalam surah al-Baqarah (2) ayat 282. Pendapat ulama Mazhab Hanafi ini juga dianut ulama Mazhab Syafi‘i. Bahkan, menurut mereka, jika dalam kesaksian itu tidak dapat dihadirkan seorang lelaki pun, saksinya harus empat orang wanita.
Apabila setelah menikah pasangan suami-istri baru mengetahui bahwa mereka adalah sepersusuan, menurut ulama Mazhab Hanafi perkawinan itu batal dengan sendirinya tanpa harus melalui proses talak. Jika perkawinan itu telah membuahkan anak, anak itu hanya dibangsakan pada ibunya dan hak waris hanya diterimanya dari ibunya. Pria yang sebelumnya adalah ayahnya kini berstatus sebagai pamannya.
Daftar Pustaka
Ibnu Rusyd. Bidayah al-Mujtahid wa Nihayah al-Muqtasid. Cairo: Maktabah Ali Shabih, t.t.
al-Jaziri, Abdurrahman. al-Fiqh ‘ala al-Madzahib al-Arba‘ah. Beirut: Dar al-Fikr, 1986.
as-San‘ani, Muhammad bin Ismail al-Kahlani. Subul as-Salam. Cairo: al-Babi al-Halabi, 1960.
Syaltut, Mahmud dan Muhammad Ali as-Sayis. Muqaranah al-Madzahib. Beirut: Dar al-Fikr, 1978.
asy-Syaukani, Muhammad bin Ali bin Muhammad. Nail al-Authar. Beirut: Dar al-Fikr, 1973.
Nasrun Haroen