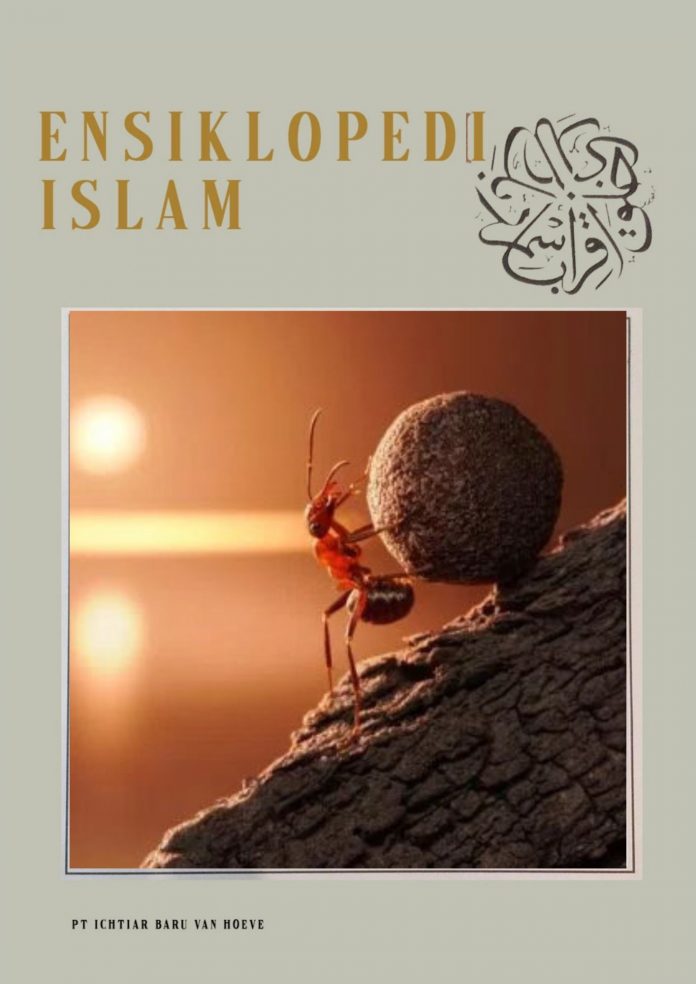Dari segi bahasa, al-garizah berarti “naluri” atau “insting”. Adapun menurut istilah, al-garizah berarti “dorongan hati atau nafsu bawaan lahir”; “pola tingkah laku turun-temurun”; dan “pembawaan alami yang secara tidak disadari mendorong untuk berbuat sesuatu”.
Penjelasan tentang garizah banyak dijumpai dalam pembahasan mengenai jiwa manusia. Menurut Muzayyin Arifin, pakar ilmu pendidikan, garizah merupakan salah satu bagian dari fitrah (potensi dasar) yang dimiliki manusia. Menurutnya, garizah adalah suatu kemampuan berbuat atau bertingkah laku tanpa melalui proses belajar dan merupakan pembawaan sejak lahir.
Menurut Jamil Shaliba, seorang ahli filsafat, garizah adalah suatu kemampuan atau daya kehidupan yang bersifat dasar yang diberikan kepada manusia agar timbul semangat pada dirinya untuk bekerja memelihara kelangsungan hidupnya. Termasuk pula ke dalam ruang lingkup garizah ini adalah daya untuk mencegah segala sesuatu yang dapat merusak dan mengancam keselamatan jiwa seseorang. Daya ini berbeda-beda kualitasnya pada setiap orang.
Menurut Shaliba, garizah (jamak: al-gara’iz) terbagi atas dua tingkatan. Pertama, gara’iz awwaliyyah atau naluri primer, yakni kemampuan pokok yang bersifat dasar yang mendorong timbulnya semangat untuk hidup yang sesuai dengan pertumbuhannya yang alami. Kedua, gara’iz Tsanawiyyah atau naluri sekunder, yakni kemampuan yang tumbuh karena melakukan pekerjaan yang dikehendaki yang selanjutnya berhubungan dengan perasaan.
Sebagian filsuf mengatakan bahwa antara garizah dan akal terdapat potensi rohani yang mendorong seseorang untuk berbuat dan berpikir. Namun ruang gerak dari kedua unsur tersebut berbeda-beda.
Garizah berhubungan khusus dengan pekerjaan yang terkait dengan kelangsungan hidup, yakni berkaitan dengan pembentukan alat-alat anggota tu-buh dan peranannya serta tidak memerlukan latihan dan pen-didikan. Adapun akal adalah pekerjaan di luar anggota tubuh dan dalam melakukan perannya membutuhkan pendidikan. Menurut Muzayyin Arifin, garizah ada 12 macam, yaitu:
(1) perasaan takut; (2) menolak sesuatu yang kotor atau menjijikan; (3) ingin mengetahui sesuatu yang menakjubkan; (4) membela diri jika mendapat serangan; (5) merendahkan diri, karena perasaan mengabdi; (6) menonjolkan diri, karena harga diri atau manja; (7) kasih sayang, karena ada perasaan halus budi; (8) berhubungan seksual, karena keinginan mengadakan reproduksi; (9) berkumpul, karena keinginan mendapatkan sesuatu yang baru; (10) mencari sesuatu, ka-rena merasa kekurangan; (11) membangun sesuatu, karena ingin mendapatkan kemajuan; dan (12) menarik perhatian orang lain, karena ingin diperhatikan orang lain.
Sementara itu, Ahmad Amin, seorang pakar di bidang etika, dalam bukunya al-Akhlaq (Ilmu Akhlak) mengakui adanya macam-macam garizah atau naluri tersebut. Namun yang terpenting menurutnya ada tiga.
(1) Naluri menjaga diri pribadi. Perasaan ini menurutnya terdapat pada semua makhluk hidup. Misalnya, sejak lahir semua hewan selalu berusaha untuk mempertahankan diri, yakni dengan berusaha mendapatkan makanan, meloloskan diri dari musuh, dan sebagainya.
Selanjutnya ia menam bahkan bahwa hewan berusaha untuk dapat hidup dalam lingkungannya, walaupun lingkungannya buruk, dan beru-saha menyesuaikan diri agar cocok dengan lingkungannya. Menurutnya, naluri ini memenuhi segala makhluk yang berada di muka bumi. Mereka semua hidup, karena mereka ingin hidup menurut nalurinya.
(2) Naluri menjaga jenis. Menurutnya, naluri atau insting ini termasuk yang paling kuat dan yang paling banyak tampak dalam kehidupan. Bukti dari naluri ini terlihat dalam percumbuan antara dua jenis makhluk yang berbeda kelamin.
Lebih lanjut Ahmad Amin mengatakan bahwa naluri ini merupakan sumber dari kelakuan manusia. Misalnya, kebanyakan perbuatan yang dilakukan oleh seorang pemuda adalah karena ingin memenuhi naluri mencintai lawan jenisnya. Jika naluri ini diatur dengan sebaik-baiknya tentu akan menjadi sumber kebahagiaan. Sebaliknya, kalau tidak diatur akan menimbulkan kesengsaraan.
Lebih lanjut dikatakannya bahwa naluri ini terkadang amat kuat dorongannya, sehingga melemahkan naluri menjaga pribadinya. Untuk ini ia mencontohkan tentang adanya orang yang dalam kehidupannya mengesampingkan kesenangan dirinya karena ingin memberikan kasih sayang kepada yang lain.
(3) Naluri takut. Naluri ini tumbuh sejak masa kanak-kanak hingga seseorang meninggal. Naluri ini menyebabkan manusia takut pada dirinya, hak miliknya, dari kawannya, dari khayalnya sendiri, dari kemiskinan, dan karena umur panjang serta datangnya kematian. Untuk mencapai kebaikan dan kemaslahatan manusia, diperlukan rasa takut yang sedang, bukan yang berlebihan.
Di luar ketiga macam naluri tersebut, Ahmad Amin me nambahkan naluri-naluri yang lain, seperti naluri memiliki, ingin mengetahui, suka bergaul, dan sebagainya. Mahmud Syaltut (ulama dan pemikir Islam dari Mesir) dalam bukunya Min Hady Al-Qur’an (Dari Petunjuk Al-Qur’an) mengatakan bahwa agar berbagai keinginan tersebut tidak saling bertabrakan dan tidak menimbulkan bencana, agama menga-turnya melalui syariat, seperti syariat pernikahan, syariat jual beli, dan lain sebagainya.
Abdul al-Qusi Aziz al-Qusi, seorang pakar ilmu jiwa dari Mesir, mengatakan bahwa naluri yang ada pada manusia senantiasa mengalami perkembangan dari waktu ke waktu, karena manusia memiliki akal pikiran yang dapat dididik. Ia mencontohkan naluri membuat tempat tinggal pada manusia yang berkembang dari masa ke masa.
Dahulu orang membuat tempat tinggal untuk melindungi diri di goa di gunung-gunung. Kini orang berdiam di gedung-gedung pencakar langit yang didukung teknologi yang maju, sehingga menimbulkan kenyamanan dan kenikmatan. Hal ini berbeda dengan insting membuat rumah pada binatang yang dari sejak dahulu hingga sekarang tidak mengalami perubahan.
Daftar Pustaka
Abdul Baqi, Muhammad Fu’ad. al-Mu‘jam al-Mufahras li Alfaˆ Al-Qur’an al-Karim. Beirut: Dar al-Fikr, 1987.
Amin, Ahmad. Etika (Ilmu Akhlak), terj. Jakarta: Bulan Bintang, 1983.
Arifin, Muzayyin. Ilmu Pendidikan Islam. Jakarta: Bumi Aksara, 1991.
Bucaille, Maurice. Asal-Usul Manusia Menurut Bibel, Al-Qur’an, Sains, terj. Bandung: Mizan, 1986.
al-Ghazali, Abu Hamid Muhammad bin Muhammad. Ihya’‘Ulum ad-Din. Beirut: Dar al-Fikr, t.t.
al-Qusy, Abdul Aziz. Ilmu Jiwa, Prinsip-Prinsip dan Implementasinya dalam Pendidikan, terj. Jakarta: Bulan Bintang, 1976.
Saliba, Jamil. al-Mu‘jam al-Falsafi. Cairo: Dar al-Kitab al-Misri, 1979.
Umarie, Barmawie. Materi Akhlak. Yogyakarta: Ramadhan, 1978.
Abuddin Nata