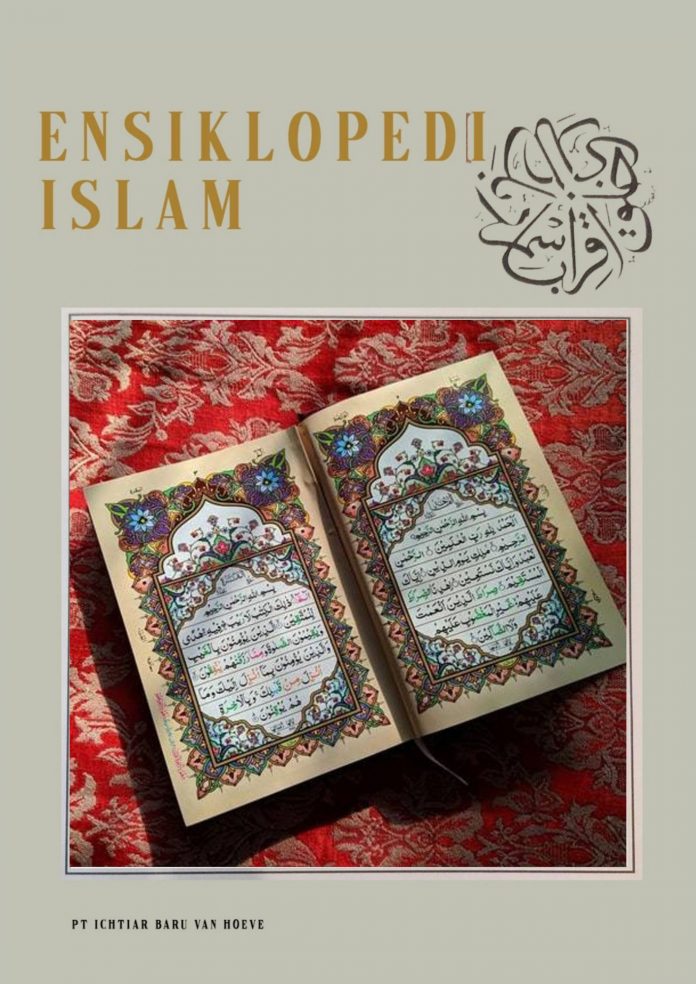Al-mutasyabihat secara kebahasaan berarti “mirip, tidak jelas, atau samar-samar”. Dalam ilmu tafsir al-mutasyabihat berarti “ayat yang mengandung makna atau pengertian yang tidak tegas atau samar-samar karena artinya berdekatan atau terdapat beberapa pengertian”. Al-mutasyabihat merupakan istilah populer dalam ilmu tafsir; lawan dari al-muhkamat (tegas, jelas).
Kedua istilah tersebut (al-mutasyabihat dan al-muhkamat) dikutip dari teks ayat Al-Qur’an:
“Dialah yang menurunkan kepadamu Alkitab (Al-Qur’an) kepada kamu. Di antara (isi)nya ada ayat-ayat yang muhkamat; itulah pokok-pokok isi Al-Qur’an dan yang lain (ayat-ayat) mutasyabihat. Adapun orang-orang yang dalam hatinya condong kepada kesesatan, maka mereka mengikuti ayat-ayat yang mutasyabihat daripadanya untuk menimbulkan fitnah dan untuk mencari-cari takwilnya, padahal tidak ada yang mengetahui takwilnya melainkan Allah. Dan orang-orang yang mendalam ilmunya berkata, ‘Kami beriman kepada ayat-ayat yang mutasyabihat, semuanya itu dari sisi kami.’ Dan tidak dapat mengambil pelajaran (daripadanya) melainkan orang-orang yang berakal” (QS.3:7).
Berdasarkan ayat di atas para ahli tafsir menggolong kan ayat Al-Qur’an dalam dua kelompok ayat, yaitu ayat muhkamat (yang mengandung pengertian tegas) dan ayat mutasyabihat.
Para ahli tafsir mengemukakan pengertian ayat mutasyabihat sebagai ayat yang mengandung makna atau pengertian yang tidak tegas atau samar-samar yang disebabkan oleh arti yang berdekatan atau oleh kemungkinan beberapa pengertian. Namun demikian di antara mereka terdapat perbedaan pendapat mengenai maksud mutasyabihat yang sesungguhnya. Pendapat mereka itu dapat disimpulkan sebagai berikut:
(1) ayat yang pemahamannya memerlukan kajian yang mendalam atau penjelasan dari luar; termasuk dalam kelompok ini ayat yang mujmal (global, lawan dari kata al-mubayyan = terperinci);
(2) ayat yang mempunyai beberapa pengertian;
(3) ayat yang pengertian sebenarnya berlainan dengan pengertian lahirnya; dan
(4) ayat tertentu dalam Al-Qur’an; dalam hal ini ayat yang mansukh (dihapus) hukumnya, ayat yang berupa huruf hija’iyah (ejaan) pada awal sebagian surat, dan ayat al-qasas (tentang sifat Tuhan).
Selain itu, para ahli tafsir juga berselisih paham mengenai kemungkinan memahami ayat mutasyabihat. Perselisihan itu muncul antara lain karena perbedaan mereka dalam memahami bentuk atau status kalimat “dan orang-orang yang mantap dalam ilmunya” dalam ayat di atas.
Para ahli memperdebatkan apakah kalimat tersebut merupakan kalimat lanjutan dari kalimat sebelumnya, yaitu dengan menganggap kata “wa” (dan) sebagai harf ‘atfi (kata penghubung) sehingga pengertiannya “tiada yang mengetahui penakwilannya kecuali Allah dan orang-orang yang mantap dalam ilmunya”, ataukah sebagai kalimat baru, yaitu dengan menganggap kata “wa” tersebut lil-ibtida’ (berfungsi sebagai pokok kalimat) sehingga pengertiannya “tiada yang mengetahui penakwilannya kecuali Allah. Adapun orang-orang yang mantap dalam ilmunya….”
Bagi kelompok pertama, ayat mu tasyabihat itu dapat dipahami karena menurut mereka, Al-Qur’an itu justru diturunkan kepada umat manusia untuk dipahami, termasuk di dalamnya ayat mutasyabihat. Akan tetapi bagi kelompok kedua, ayat mutasyabihat tidak dapat dipahami manusia karena menurut mereka, ayat mutasyabihat itu diturunkan untuk menguji iman mereka.
Ayat Sifat. Ayat sifat berkaitan dengan sifat Tuhan yang mengarah pada sifat tajsim (menganggap Tuhan mempunyai bentuk; antropomorfisme). Persoalan ini merupakan inti permasalahan dalam ayat mutasyabihat. Oleh karena itu tidak heran apabila sebagian ahli tafsir membatasi ayat mutasyabihat pada ayat sifat tersebut. Berkaitan dengan persoalan ini muncul tiga golongan.
(1) Ahl at-Ta’wil atau golongan Mu’awwilah, yakni golongan yang menakwilkan ayat sifat dengan mengutamakan pengertian yang tersirat dari ayat itu. Misalnya, menakwilkan kata “al-yad” (tangan; yang dimaksud adalah tangan Tuhan) pada firman-Nya:
“Hai iblis, apakah yang menghalangi kamu sujud kepada yang telah Ku-ciptakan dengan kedua tanganku…” (QS.38:75) sebagai kekuatan atau kekuasaan Tuhan, kata “al-wajh” (wajah) sebagai zat atau wujud Tuhan, dan “Tuhan duduk di atas arasy (singgasana)” sebagai berkuasa. Penganut paham ini antara lain adalah aliran Muktazilah, Syiah, dan beberapa tokoh Asy‘ariyah seperti Imam al-Haramain al-Juwaini.
(2) as-sifatiyyah al-Mutawaqqifah, yaitu golongan yang mengakui adanya sifat tersebut seperti yang tercantum dalam ayat, tetapi mereka tidak berani menjabarkannya secara tegas. Mereka percaya, berdasarkan ayat sifat tersebut, Tuhan mempunyai tangan, tetapi tidak mengetahui bagaimana tangan Tuhan itu sesungguhnya. Demikian pula sifat wajah, mata, dan sebagainya.
(3) as-sifatiyyah al-Musyabbihah, yaitu golongan yang menyerupakan sifat itu dengan sifat makhluk atau manusia.
Menurut Ragib al-Isfahani (ahli fikih dan tafsir), tasyabuh (ke-mutasyabihatan) suatu ayat dapat terjadi pada tiga aspek, yaitu:
(1) pada aspek kata, seperti pada kata al-yad (tangan) dan kata al-‘ain (mata) yang mempunyai beberapa pengertian;
(2) pada aspek makna, seperti pada makna sifat Tuhan dan sifat hari kiamat, yang tidak tergambarkan oleh manusia tidak dapat secara pasti, dan
(3) pada aspek kata dan makna sekaligus, seperti pada kata atau makna ayat: “…Bunuhlah al-musyrikin (kaum musyrikin) di mana saja kamu dapati mereka…” (QS.9:5); kata dan makna al-musyrikin (jamak dari kata al-musyrik = orang musyrik) dapat berarti “seluruh, sebagian, atau orang tertentu saja dari kaum musyrikin”.
Adapun hikmah diturunkannya ayat mutasyabihat, menurut Fakhruddin ar-Razi yang merangkum pandangan ulama sebelumnya, terdiri atas lima hal:
(1) menambah pahala, karena dengan diturunkannya ayat mutasyabihat seorang peneliti akan berusaha lebih giat lagi untuk mencari kebenaran dan dalam hal ini terdapat pahala yang besar;
(2) memperluas wawasan, karena dengan sendirinya seorang peneliti didorong untuk membandingkan pandangannya atau pandangan mazhabnya mengenai maksud ayat tersebut dengan pandangan orang lain atau mazhab lain, sehingga ia akan menyimpulkan atau sampai pada pendapat yang benar;
(3) menumbuhkan sikap ilmiah dan sekaligus memerangi taklid, karena dengan sendirinya ia akan meneliti ayat tersebut dengan menggunakan nalar, dasar, dan bukti;
(4) menambah ilmu pengetahuan, karena untuk mengetahui maksud ayat tersebut dengan baik ia harus mendalami berbagai disiplin ilmu yang terkait, seperti ilmu bahasa, gramatika, dan usul fikih; dan
(5) sebagai isyarat bahwa secara umum kandungan
Al-Qur’an mencakup kalangan khawas (orang tertentu) dan awam. Sifat orang awam adalah sulit memahami esensi sesuatu. Misalnya, mereka sulit memahami suatu wujud yang tidak mempunyai materi atau yang tidak berdimensi.
Dalam hal ini bahasa yang digunakan kepada mereka adalah bahasa yang sederhana yang sesuai dengan kemampuan mereka supaya mereka dapat mencernanya, akan tetapi di balik ungkapan itu terkandung makna yang sebenarnya.
Dengan demikian, pada mulanya ayat itu bermakna mutasyabihat, tetapi kemudian, setelah jelas apa yang dimaksud sebenarnya, maknanya menjadi muhkamat. Menurut ar-Razi, inilah inti diturunkannya ayat mutasyabihat.
DAFTAR PUSTAKA
as-Salih, Subhi. Mabahits fi ‘Ulum Al-Qur’an. Beirut: Dar al-‘Ilm li al-Malayiyin, 1985.
ash-Shiddieqy, T.M. Hasbi. Ilmu-Ilmu Al-Qur’an. Jakarta: Bulan Bintang, 1972.
as-Suyuti, Jalalaluddin. al-Itqan fi ‘Ulum Al-Qur’an. Beirut: Dar al-Fikr, 1979.
Zarqani. Manahil al-‘Irfan fi ‘Ulum Al-Qur’an. Cairo: Isa al-Babi al-Halabi, t.t.
UMAR SHAHAB
__