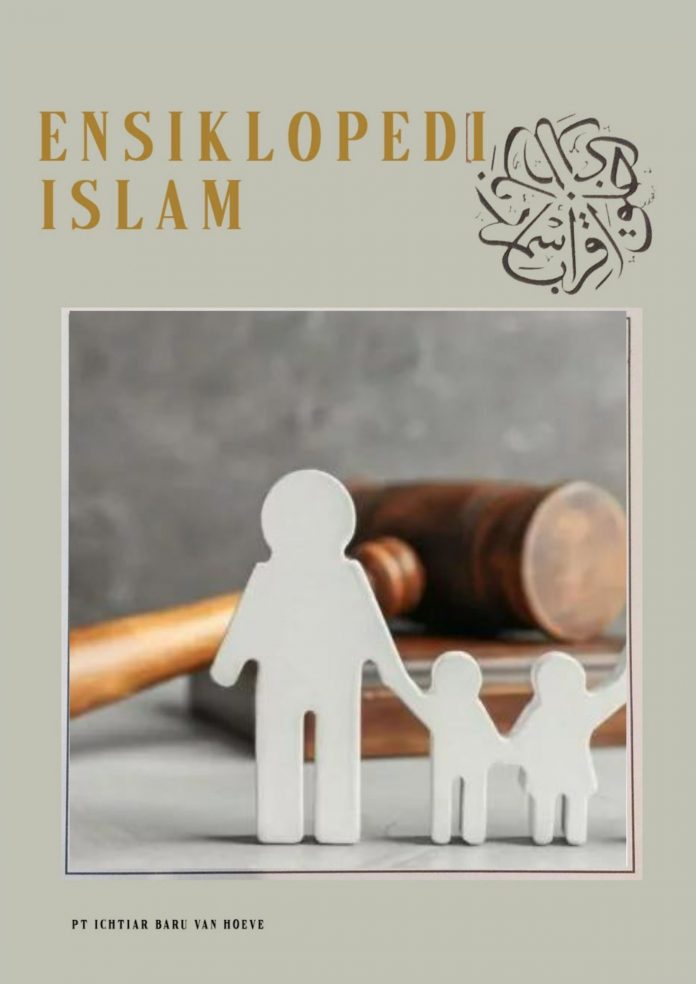Secara kebahasaan, al-hajr berarti “akal”. Kata dengan arti tersebut ada dalam surah al-Fajr (89) ayat 5: “Pada yang demikian itu terdapat sumpah (yang dapat diterima) oleh orang-orang yang berakal.” Istilah al-hajr dalam fikih berkenaan dengan kecakapan seseorang bertindak secara hukum. Hajara ‘alaihi hajran berarti “orang yang dilarang bertindak secara hukum”. Dalam hukum perdata, al-hajr berarti “pengampuan”.
Sebagian ulama Mazhab Hanafi mendefinisikan al-hajr sebagai “larangan melaksanakan akad dan bertindak secara hukum dalam bentuk perkataan”. Jika seseorang yang berada dalam pengampuan melakukan tindakan hukum dalam bentuk perkataan, seperti jual beli atau hibah, tindakannya itu tidak dapat dilaksanakan dan segala akibat akad tersebut tidak berlaku, karena akadnya sendiri tidak sah.
Ulama Mazhab Hanafi lainnya mendefinisikannya dengan “larangan khusus yang berkaitan dengan pribadi tertentu dalam tindakan hukum tertentu pula”. Apabila orang yang dalam pengampuan melakukan suatu tindakan hukum yang bersifat ucapan atau pernyataan, transaksi yang dilakukannya itu tidak sah kecuali apabila ia mendapatkan izin dari walinya (yang mengampunya).
Akan tetapi, jika ia melakukan tindakan hukum berupa perbuatan dan tindakannya itu mempunyai risiko kerugian harta benda, maka ia harus menggantinya dengan hartanya apabila ia memiliki harta atau memintanya kepada walinya. Namun, hukuman yang bersifat fisik tidak boleh dikenakan kepada orang yang berada dalam pengampuan tersebut.
Ulama Mazhab Maliki mengemukakan definisi lain. Menurut mereka, al-hajr adalah status hukum yang diberikan syarak (hukum Islam) terhadap seseorang sehingga ia dilarang melakukan tindakan hukum di luar batas kemampuannya atau melakukan suatu tindakan pemindahan hak milik melebihi sepertiga hartanya.
Orang yang dilarang bertindak hukum di luar batas kemampuannya mencakup antara lain anak kecil, orang gila, orang dungu, dan orang yang jatuh pailit. Mereka dilarang melakukan tindakan hukum seperti jual beli atau perbuatan pemindahan hak milik lainnya. Apabila mereka tetap mau melakukannya, tindakan mereka amat tergantung pada izin walinya.
Adapun orang yang dilarang memindahtangankan hak miliknya melebihi sepertiga hartanya adalah orang sakit yang diduga keras tidak akan sembuh lagi dan penyakitnya itu mengakibatkan ia meninggal. Orang seperti ini tidak dilarang melakukan segala bentuk transaksi jual beli.
Adapun yang berkenaan dengan tindakan pemindahan hak milik secara sukarela, seperti ber sedekah, wakaf atau hibah, berlaku baginya pembatasan sampai sepertiga hartanya. Lebih dari itu tidak dibenarkan.
Ulama Mazhab Syafi‘i dan Mazhab Hanbali mendefinisikan al-hajr dengan “larangan melakukan tindakan hukum terhadap seseorang, baik larangan itu datang dari syarak (seperti larangan tindakan hukum yang ditujukan kepada anak kecil, orang gila, dan orang dungu), maupun dari hakim (seperti larangan dari hakim kepada seorang pedagang untuk menjual barangnya melebihi harga pasar)”.
Menurut ulama fikih, dasar hukum al-hajr adalah firman Allah SWT dalam surah an-Nisa’ (4) ayat 5–6 yang berarti:
“Dan janganlah kamu serahkan kepada orang-orang yang belum sempurna akalnya, harta (mereka yang ada dalam kekuasaanmu) yang dijadikan Allah sebagai pokok kehidupan. Berilah mereka belanja dan pakaian (dari hasil harta itu) dan ucapkanlah kepada mereka kata-kata yang baik. Dan ujilah anak yatim itu sampai mereka cukup umur untuk kawin. Kemudian jika menurut pendapatmu mereka telah cerdas (pandai memelihara harta), maka serahkanlah kepada mereka harta-hartanya….”
Dalam ayat lain Allah SWT juga berfirman, “…Jika yang berutang itu orang yang lemah akalnya atau lemah (keadaannya) atau dia sendiri tidak mampu mengimlakkan, maka hendaklah walinya mengimlakkan dengan jujur…” (QS.2:282).
Dalam hadis diceritakan bahwa Rasulullah SAW pernah menjadikan Mu‘az bin Jabal di bawah pengampuannya karena Mu‘az terlilit utang. Rasulullah SAW lalu menjual harta Mu‘az dan melunasi utangnya. Demikian juga Rasulullah SAW pernah menjadikan Usman bin Affan dalam pengampuannya, karena sikap mubazir yang dilakukan Usman (HR. al-Baihaqi, Daruqutni, dan al-Hakim dari Ka‘b bin Malik).
Dilihat dari tujuannya, al-hajr dapat dibagi menjadi dua:
(1) untuk kemaslahatan orang yang berada di bawah pengampuan, seperti anak kecil, orang gila, orang dungu, dan orang yang bersikap mubazir; dan (2) untuk kemaslahatan orang lain, seperti orang pailit yang terlilit utang sampai tidak mampu membayarnya kembali, orang sakit yang diduga keras akan meninggal, dan orang yang menggadaikan hartanya sementara ia tidak mampu lagi menebus hartanya itu.
Penyebab seseorang berada di bawah pengampuan bermacam-macam. Sebagian disepakati ulama fikih, seperti al-hajr terhadap anak kecil dan orang gila yang tidak memiliki kemampuan akal. Ulama berselisih tentang sebab pengampuan orang dungu dan orang berutang. Pengampuan terhadap mereka bukan karena mereka tidak mempunyai kecakapan bertindak hukum, tetapi dimaksudkan untuk menghindarkan orang lain mendapat mudarat dari tindakannya atau mencegah terjadinya mudarat pada mereka sendiri.
Perbedaan pandangan tersebut juga menyebabkan perbedaan dalam menentukan akibat hukum dari tindakan mereka. Ulama fikih (fukaha) membahas persoalan ini sebagai berikut.
(1) Al-hajr terhadap tindakan hukum anak kecil. Ulama Mazhab Hanafi dan Maliki membedakan anak kecil yang belum mumayiz (dapat membedakan sesuatu yang baik dan sesuatu yang buruk; menurut mereka, di bawah usia 7 tahun) dan anak kecil yang sudah mumayiz.
Pembedaan ini didasarkan pada hadis Rasulullah SAW yang berisi perintah agar orangtua menyuruh anaknya mengerjakan salat apabila telah berumur tujuh tahun (HR. Ahmad, Abu Dawud, dan al-Hakim dari Abdullah bin Amr). Anak kecil yang melakukan tindakan hukum yang bersifat perbuatan, seperti merusak barang orang lain, dikenai sanksi hukum, seperti membayar ganti rugi, karena tidak ada pengampuan dalam perbuatan.
Lain halnya apabila tindakan hukum itu bersifat perkataan atau pernyataan. Jika anak yang belum mumayiz melakukan tindakan hukum itu, maka perkataan atau pernyataannya dianggap batal, baik tindakannya itu menguntungkan maupun merugikan dirinya, karena ia dinilai belum cakap bertindak secara hukum.
Namun, jika tindakan itu dilakukan oleh anak yang sudah mumayiz, perlu dibedakan apakah tindakan hukum itu menguntungkan atau merugikan dirinya. Jika tindakan itu menguntungkan dirinya, seperti menerima wakaf atau hibah dari orang lain, tindakannya itu dapat dibenarkan dan sah tanpa harus ada justifikasi dari walinya.
Apabila tindakan itu merugikan dirinya, seperti menghibahkan atau mewakafkan hartanya kepada orang lain, tindakan itu dianggap tidak sah dan tidak pernah terjadi meskipun diizinkan oleh walinya. Jika tindakan itu bersifat antara menguntungkan dan merugikan bagi dirinya, seperti jual beli dan sewa-menyewa, transaksi itu sangat bergantung pada izin walinya. Jika walinya mengizinkan, tindakan hukum itu sah dan dilaksanakan. Akan tetapi, jika walinya tidak mengizinkan, tindakan itu batal.
Berbeda halnya dengan pendapat ulama Mazhab Syafi‘i dan Hanbali. Menurut mereka, tindakan hukum anak kecil, baik belum mumayiz maupun sudah, tidak sah. Lebih jauh ulama Mazhab Syafi‘i mengatakan bahwa meskipun anak itu mumayiz dan tindakannya itu diizinkan walinya, tindakan itu tetap tidak sah. Namun, ulama Mazhab Hanbali menganggap sah tindakan anak yang telah mumayiz apabila diizinkan walinya.
(2) Al-hajr terhadap tindakan hukum orang gila. Dalam fikih Islam dibedakan antara gila yang bersifat permanen (tetap) dan gila yang bersifat temporer (untuk sementara waktu). Tindakan hukum orang gila yang permanen disamakan dengan anak kecil yang belum mumayiz. Adapun tindakan hukum orang gila yang temporer dianggap tidak sah apabila gilanya kambuh. Akan tetapi, tindakan hukumnya dianggap sah jika ia sembuh dari gilanya dan ia bebas dari ikatan pengampuan.
(3) Al-hajr terhadap tindakan hukum orang bodoh/dungu. Dalam fikih Islam orang yang biasa menghambur-hamburkan hartanya tanpa tujuan yang diridai syarak, seperti membelanjakan hartanya untuk kepuasan nafsu seksualnya, membeli khamar, dan berjudi, atau pedagang yang tidak mengerti cara berdagang sehingga sering ditipu, harus dikenakan pengampuan dan segala tindakan hukum yang merugikan dirinya dianggap batal.
Mengenai hal ini, ada perbedaan pendapat di kalangan ulama Mazhab Hanafi. Imam Abu Hanifah (Imam Hanafi) mengatakan bahwa tindakan hukum orang bodoh yang telah balig dan berakal dianggap sah meskipun merugikan dirinya sendiri. Ia mengatakan bahwa menetapkan mereka di bawah pengampuan merupakan pengekangan terhadap hak asasi mereka.
Sementara itu, Imam Abu Yusuf dan Muhammad bin Hasan asy-Syaibani (keduanya sahabat Abu Hanifah) mengatakan bahwa orang bodoh/dungu berada di bawah pengampuan untuk kemaslahatan diri mereka sendiri. Pendapat ini sejalan dengan pendapat jumhur (mayoritas) ulama, yang didasarkan kepada firman Allah SWT yang berarti: “Dan janganlah kamu serahkan kepada orang-orang yang belum sempurna akalnya…” (QS.4:5).
Dengan demikian, menurut jumhur ulama dan kedua sahabat Abu Hanifah di atas, tindakan hukum orang bodoh/dungu disamakan dengan tindakan hukum anak kecil dan orang gila permanen. Apabila sifat bodoh/dungu itu telah hilang, segala tindakan hukum mereka dianggap sah.
(4) Al-hajr untuk kemaslahatan umum. Ulama Mazhab Hanafi membolehkan menetapkan seseorang berada di bawah pengampuan jika ia sering mengganggu kemas lahatan umum, karena kemaslahatan umum harus didahulukan daripada kemaslahatan pribadi; misalnya seorang dokter yang merugikan pasien karena sering memberi obat dan diagnosis keliru atau seorang mufti yang sering memberi fatwa yang menyesatkan dan membingungkan umat. Menurut mereka, orang seperti ini boleh ditetapkan sebagai orang yang berada di bawah pengampuan.
(5) Al-hajr terhadap orang sakit yang diduga keras akan meninggal. Menurut ulama mazhab yang empat (Hanafi, Maliki, Syafi‘i, dan Hanbali), jika seseorang dalam keadaan sakit yang secara medis tidak akan sembuh dan diduga akan meninggal, tindakan hukumnya harus dibatasi dan ia ditetapkan sebagai orang yang berada di bawah pengampuan.
Ulama Mazhab Maliki memasukkan orang yang diduga keras akan menghadapi kematian, seperti orang yang pergi berperang dan orang yang akan dihukum mati, ke dalam kelompok ini meskipun orang tersebut tidak sakit. Tindakan hukum yang dibatasi terhadap orang seperti ini adalah tindakan yang bersifat mengeluarkan harta tanpa imbalan, seperti wakaf, hibah, dan sedekah.
Apabila orang sakit yang diduga keras akan meninggal tersebut meninggal dunia dan telah mengeluarkan harta tanpa imbalan itu, tindakan hukumnya hanya dapat disahkan jika jumlahnya tidak melebihi sepertiga harta. Namun, jika ia ternyata berumur panjang dan hidup normal kembali, seluruh tindakan hukumnya dianggap sah.
(6) Al-Hajr terhadap orang yang jatuh pailit. Ulama sepakat menyatakan bahwa orang yang jatuh pailit dan mempunyai utang yang cukup besar pada beberapa orang ditetapkan sebagai orang yang berada di bawah pengampuan. Akibat dari status pengampuan ini adalah:
(a) orang tersebut dilarang melakukan tindakan hukum terhadap hartanya karena pada harta itu terkait hak orang yang memberi utang kepadanya;
(b) orang tersebut boleh dipenjarakan berdasarkan keputusan hakim untuk kemaslahatan dirinya dan para pemberi utang kepadanya
(c) hartanya dijual untuk membayar utangnya; dan
(d) menurut Abu Hanifah, Imam Abu Yusuf, dan Muhammad bin Hasan asy-Syaibani, orang tersebut harus dijaga terus-menerus jika ia tidak dipenjarakan. Akan tetapi, ulama Mazhab Maliki, Syafi‘i, dan Hanbali berpendapat bahwa orang tersebut tidak perlu diawasi terus-menerus jika ia telah ditetapkan sebagai seorang pailit, sehingga ia mempunyai kesempatan berusaha untuk membayar utangnya. Alasan mereka adalah firman Allah SWT dalam surah al-Baqarah (2) ayat 280 yang berarti:
“Dan jika (orang berutang itu) dalam kesukaran, maka berilah tangguh sampai dia berkelapangan. Dan menyedekahkan (sebagian atau semua utang) itu, lebih baik bagimu jika kamu mengetahui.”
Status pengampuan seseorang akan hilang apabila faktor penyebabnya hilang pula. Status pengampuan anak kecil hilang secara otomatis jika ia telah balig berakal (menurut ulama Mazhab Hanafi dan Maliki, setelah mencapai umur 7 tahun), telah sembuh (bagi orang gila), dan telah cerdas kembali (bagi orang bodoh/dungu).
Bagi orang yang berada di bawah pengampuan karena pailit, menurut ulama Mazhab Syafi‘i dan Hanbali, statusnya bisa kembali normal setelah semua utangnya dibayar. Namun, ada juga yang berpendapat, karena al-hajr itu ditetapkan oleh hakim, maka yang mencabutnya pun harus hakim.
Daftar Pustaka
Ibnu Qayyim al-Jauziah. A‘lam al-Muwaqi‘in ‘an Rabbil ‘alamin. Beirut: Dar al-Fikr, 1977.
Ibnu Qudamah. al-Mugni. Riyadh: Maktabah ar-Riyadh al-Hadisah, 1981.
Ibnu Rusyd. Bidayah al-Mujtahid wa Nihayah al-Muqtashid. Beirut: Dar al-Fikr. 1978.
al-Jaziri, Abdurrahman. Kita al-Fiqh ‘Ala Madzahib al-Arba‘ah. Libanon: Dar al-Fikr, 1972.
al-Kahlani, Subul as-Salam. Cairo: Mustafa al-Babi al-Halabi, 1960.
al-Kasani. Badha’i as-Shana’i. Cairo: Mustafa al-Babi al-Halabi, t.t.
al-Kurdi, Ahmad al-Hajji. Fiqh al-Muawadah. Damascus: Matabi’ Mu’assasah al-Wahdah, 1981.
Sabiq, Sayid. Fiqh as-Sunnah. Beirut: Dar al-Fikr, 1983.
az-Zarqa, Mustafa Ahmad. al-Madkhal al-Fiqh al-‘amm: al-Fiqh al-Islami fi Saubih al-Jadid. Beirut: Dar al-Fikr, 1976.
Nasrun Haroen