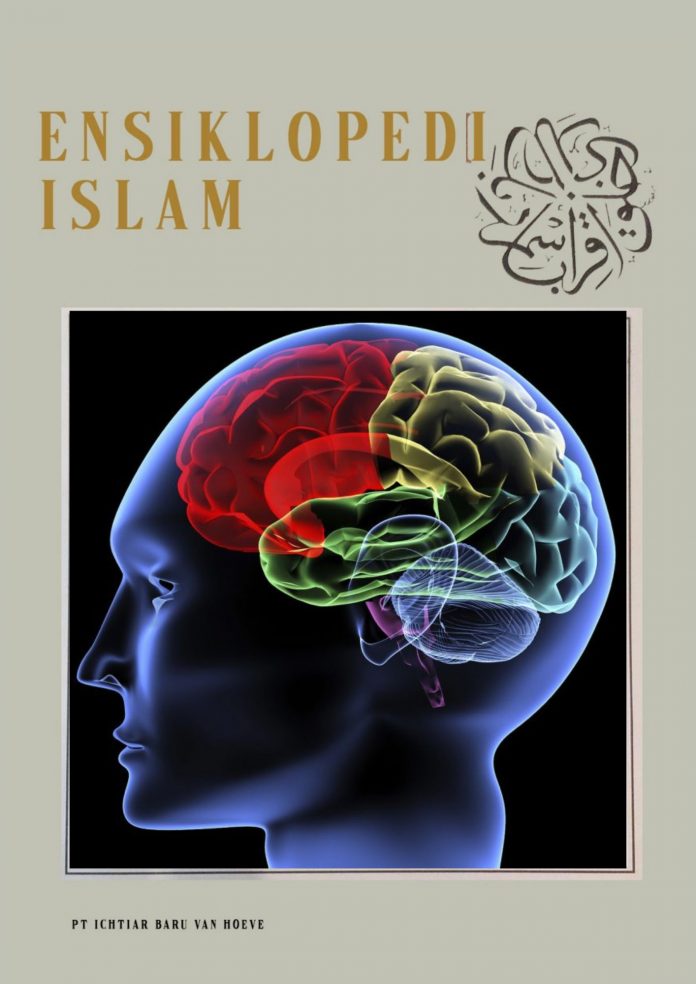Daya pikir dalam diri manusia dan salah satu daya jiwa yang mengandung arti “berpikir”, “memahami”, dan “mengerti”, disebut akal. Asal kata ‘aql adalah ‘aqala yang berarti “mengikat dan menahan”. Pada zaman Jahiliah orang berakal (‘aqil) adalah orang yang dapat menahan amarah dan mengendalikan nafsu, sehingga dapat bersikap bijaksana dalam menghadapi persoalan.
Kata ‘aql sebagai masdar (kata benda) dari ‘aqala tidak didapati dalam Al-Qur’an, namun bentukan kata dari ‘aqala tersebut terdapat dalam bentuk fi‘l mudhari‘ (kata kerja) sebanyak 49 buah dan tersebar di berbagai surah dalam Al-Qur’an. Kata-kata itu, misalnya, adalah ta‘qilun dalam surah al-Baqarah (2) ayat 44, ya‘qilun dalam surah al-Furqan (25) ayat 44 dan surah Yasin (36) ayat 68, na‘qilu dalam surah al-Mulk (67) ayat 10, ya‘qiluha dalam surah al-‘Ankabut (29) ayat 43, dan ‘aqaluhu dalam surah al-Baqarah (2) ayat 75.
Dari banyaknya penggunaan kata yang seasal dengan kata ‘aqala, dipahami bahwa Al-Qur’an sangat menghargai akal; dan bahkan Khitab Syar‘i (kitab hukum Allah) hanya ditujukan kepada orang yang berakal. Banyak sekali ayat yang mendorong manusia untuk mempergunakan akalnya. Hadis Nabi SAW juga banyak sekali yang menunjukkan tingginya posisi akal dalam syariat Islam.
Di samping kata ‘aqala, Al-Qur’an juga mempergunakan kata yang menunjukkan arti berpikir tersebut, seperti nazara yang berarti melihat secara abstrak (berpikir), dalam Al-Qur’an terdapat pada lebih dari 120 ayat; tafakkara yang berarti berpikir terdapat pada 18 ayat; faqiha yang berarti memahami terdapat pada 20 ayat; tadabbara yang juga semakna dengan ‘aqala terdapat dalam 8 ayat; dan tadzakkara yang berarti mengingat terdapat dalam 100 ayat.
Pengertian yang jelas tentang akal ini didapati dalam pembahasan para filsuf Islam. Al-Kindi mengemukakan bahwa dalam jiwa manusia terdapat tiga daya, yaitu daya bernafsu yang bertempat di perut, daya berani di dada, dan daya berpikir di kepala. Akal sebagai daya berpikir yang terdapat di kepala terbagi pula menjadi dua, yaitu akal praktis dan akal teoretis. Akal praktis adalah akal yang menerima arti yang berasal dari materi melalui indra pengingat.
Akal teoretis menangkap arti murni, yaitu arti yang tak pernah ada dalam materi, seperti Tuhan, roh, dan malaikat. Akal praktis memusatkan diri pada alam materi, sedangkan akal teoretis sebaliknya bersifat metafisis, mencurahkan perhatian pada alam immateri.
Akal teoretis ini oleh Ibnu Sina dibagi menjadi empat tingkatan, yaitu (a) akal materiil, yang semata-mata mempunyai potensi untuk berpikir dan belum dilatih walaupun sedikit; (b) akal bakat, yang telah mulai dilatih berpikir tentang hal yang abstrak; (c) akal aktual, yaitu akal yang telah dapat berpikir tentang hal yang abstrak, dan dapat ia keluarkan setiap saat apabila dikehendaki; dan (d) akal perolehan, yaitu akal yang telah sanggup berpikir tentang hal abstrak dengan tidak memerlukan daya upaya.
Akal ini telah sangat terlatih dengan hal yang abstrak, sehingga hal yang bersifat abstrak selamanya terdapat dalam akal perolehan ini; dan akal seperti inilah yang sanggup menerima limpahan ilmu pengetahuan dari Akal Aktif, atau yang dinamakan juga oleh al-Farabi sebagai Akal Kesepuluh. Yang dimaksud dengan Akal Kesepuluh menurut filsafat emanasi al-Farabi adalah Malaikat Jibril.
Al-Farabi dalam filsafat emanasinya membagi akal tersebut menjadi sepuluh macam yang berawal dari pancaran Tuhan. Tuhan sebagai akal, menurut al-Farabi, berpikir tentang diri-Nya. Pemikiran tersebut merupakan daya, dan dari daya pemikiran Tuhan yang besar dan hebat itu timbul mawjud (benda) lain. Tuhan merupakan wujud pertama, dan dengan pemikiran itu timbul wujud kedua yang juga punya substansi, dan dia disebut Akal Pertama.
Wujud kedua berpikir tentang wujud pertama, dan dari pemikiran ini timbullah wujud ketiga yang disebut Akal Kedua. Wujud kedua atau Akal Pertama berpikir tentang dirinya, dan muncullah Langit Pertama. Selanjutnya wujud ketiga (Akal Kedua) berpikir tentang Tuhan, timbullah wujud keempat atau Akal Ketiga; dan tatkala wujud ketiga atau Akal Kedua ini berpikir tentang dirinya, muncullah bintang. Akal Ketiga berpikir tentang diri Tuhan dan tentang dirinya, maka muncullah Akal Keempat dan Saturnus.
Dari Akal Keempat muncul Akal Kelima dan Jupiter, dari Akal Kelima muncul Akal Keenam dan Mars, dari Akal Keenam muncul Akal Ketujuh dan Matahari, dari Akal Ketujuh muncul Akal Kedelapan dan Venus, dari Akal Kedelapan muncul Akal Kesembilan dan Mercurius, dan dari Akal Kesembilan muncul Akal Kesepuluh dan Bulan. Pada pemikiran Akal Kesepuluh berhentilah munculnya akal; tetapi dari Akal Kesepuluh muncul Bumi dan roh serta materi pertama yang menjadi dasar dari keempat unsur: api, udara, air, dan tanah. Setiap akal tersebut mengatur planetnya masing-masing.
Akal inilah yang dikatakan malaikat tersebut. Demikian akal menurut pandangan para filsuf Islam, yang menurut mereka akal tersebut adalah suatu daya untuk memperoleh ilmu pengetahuan.
Para teolog juga membahas kedudukan akal sebagai daya berpikir yang terdapat dalam diri manusia. Pembahasan mereka berkisar sekitar apakah akal mampu untuk mengetahui Tuhan, berterima kasih kepada Tuhan, mengetahui baik dan buruk, serta kewajiban melakukan yang baik dan menjauhi yang buruk. Dalam keempat permasalahan inilah terjadi pembahasan dan polemik yang panjang dan membawa implikasi yang jauh dalam posisi akal menurut pandangan masing-masing.
Kaum Muktazilah beranggapan bahwa akal cukup mampu untuk mengetahui dan melaksanakan keempat hal di atas, sekalipun wahyu belum turun untuk menuntun manusia. Berdasarkan pendapat ini, mereka digelari sebagai kaum rasionalis Islam.
Golongan Asy‘ariyah menyatakan bahwa dari keempat masalah tersebut manusia hanya mampu mengetahui Tuhan melalui akalnya sebelum datangnya wahyu, sedangkan tiga masalah lainnya tidak dapat dicapai oleh akal. Kaum Maturidiyah tampaknya terpecah dua dalam menghadapi keempat permasalahan di atas.
Maturidiyah Samarkand, yang dimotori oleh Abu Mansur Muhammad al-Maturidi sendiri, mengatakan bahwa tiga dari masalah tersebut dapat dicapai oleh akal, yaitu mengetahui Tuhan, kewajiban berterimakasih kepada Tuhan, dan mengetahui mana yang baik dan mana yang buruk. Kewajiban melakukan yang baik dan meninggalkan yang buruk hanya dapat dicapai melalui wahyu.
Adapun kaum Maturidiyah Bukhara, yang dimotori oleh Imam Ali Muhammad al-Bazdawi, mengatakan bahwa yang dapat dicapai akal tersebut hanya dua, yaitu mengetahui Tuhan dan mengetahui mana yang baik dan mana yang buruk; sedangkan untuk mengetahui kewajiban yang dua lagi harus melalui wahyu, bukan dengan akal.
Kemampuan akal sebagai daya berpikir yang ada dalam diri manusia juga menjadi permasalahan yang menarik perhatian kalangan usul fikih. Artinya para usuli juga memperdebatkan masalah penggunaan akal ini dalam berijtihad, sehingga muncullah apa yang dikenal dengan ahlurra’yi sebagai bandingan ahlulhadis (orang yang berpegang pada hadis).
Namun demikian masing-masing pihak tetap menganggap Al-Qur’an dan sunah sebagai sumber utma hukum Islam. Perbedaan tentang penggunaan akal baru muncul tatkala ijtihad dilakukan dalam keadaan tidak ada nas yang mengatur secara jelas permasalahan yang sedang dihadapi atau ada hadis ahad (hadis yang diriwayatkan oleh seorang perawi) yang kandungannya bertentangan dengan pendapat akal, apakah hadis dipakai atau pendapat akal yang didahulukan. Kalangan Hanafiyah (pengikut Imam Hanafi), yang dikenal banyak mempergunakan akal dalam berijtihad, memberikan syarat yang cukup ketat untuk dapat diterimanya sebuah hadis ahad.
Namun, sebagaimana dikatakan di atas, kalangan ahli usul ini tetap menyandarkan pendapat mereka kepada Al-Qur’an dan sunah. Sekalipun dalam hasil ijtihad itu pendapat akal lebih dominan, dalam kenyataannya hasil ijtihad tersebut baru mereka anggap sah jika ada legitimasi dari syarak. Oleh sebab itu, sekalipun kalangan Hanafiyah banyak menolak hadis ahad, dalam buku fikih mereka banyak sekali didapati hadis ahad, dan kadang-kadang hadis ahad yang mereka pakai tidak diterima kalangan ahlulhadis.
Dalam masalah pembahasan kekuatan akal ini, Najmuddin at-Tufi, seorang ulama fikih Mazhab Hanbali yang dalam perjalanan hidupnya pernah menganut paham Syiah dan Muktazilah, berpendapat bahwa pendapat akal itu harus lebih didahulukan dari dalil syar‘i (nas dan ijmak) apabila di antara keduanya terjadi pertentangan, karena akal merupakan dalil syar‘i tersendiri dalam mengistinbatkan hukum.
Pendapatnya ini dipaparkan ketika ia memberi syarah Kitab al-Arba‘in an-Nawawiyyah (Kitab yang Berisi Empat Puluh Hadis Pilihan), khususnya hadis Nabi SAW yang diriwayatkan Ibnu Majah Ahmad “la dharara wa la dhirar fi al-Islam” (tidak boleh memudaratkan [orang lain], dan tidak boleh pula dimudaratkan [orang lain] di dalam Islam). Dari hadis ini ia menyimpulkan bahwa kemaslahatan itu merupakan tujuan syarak yang tertinggi. Dengan demikian, jika suatu maslahat (menurut pendapat akal) bertentangan dengan nas Al-Qur’an dan sunah atau ijmak, maka didahulukan maslahat tersebut.
Pendapat Najmuddin ini tidak dapat diterima jumhur karena Syari‘ (Pembuat Hukum) dalam pengertian usul fikih adalah Allah dan Rasul-Nya. Maka tidak mungkin pendapat akal didahulukan dari Khitab Syari‘ itu sendiri. Jumhur fukaha berpendapat bahwa pendapat akal yang dapat diterima adalah pendapat yang didukung nas. Maslahat bagi jumhur dapat diterima jika ia mendapat dukungan dari nas atau ijmak, tetapi yang tidak didukung sama sekali oleh nas atau ijmak, apakah dukungan terhadap maslahat tersebut secara khusus ataupun secara umum (maslahah garibah), tidak dapat diterima. Lebih ditolak lagi jika maslahat yang dihasilkan akal tersebut bertentangan dengan nas dan ijmak (maslahah mulgah).
Daftar Pustaka:
Abdul Baqi, Muhammad Fu’ad. al-Mu‘jam al-Mufahras li Alfaz Al-Qur’an al-Karim. Beirut: Dar al-Fikr, 1992.
al-Bazdawi. al-Farq bain al-Firaq. Beirut: Dar al-Fikr, 1982.
Hassan, Husain Hamid. Nazariyyah al-Maslahah fi al-Fiqh al-Islami. Cairo: Dar an-Nahdah al-‘Arabiyyah, 1971.
Nasution, Harun. Akal dan Wahyu dalam Islam. Jakarta: UI-Press, 1986.
Rida, Muhammad Rasyid. Tafsir Al-Qur’an al-Hakim (al-Manar). Cairo: Dar al-Manar, 1953.
Shihab, M. Quraish. Membumikan Al-Qur’an: Fungsi dan Peran Wahyu dalam Kehidupan Masyarakat. Bandung: Mizan, 1992.
at-Turabi, Hasan. Tarikh al-Firaq al-Islamiyyah. Beirut: Dar al-Fikr, 1982.
Zaid, Mustafa. al-Maslahah fi at-Tasyri‘ al-Islami wa Najmuddin at-tufi. Cairo: Dar al-Fikr al-‘Arabi, 1964.
Nasrun Haroen