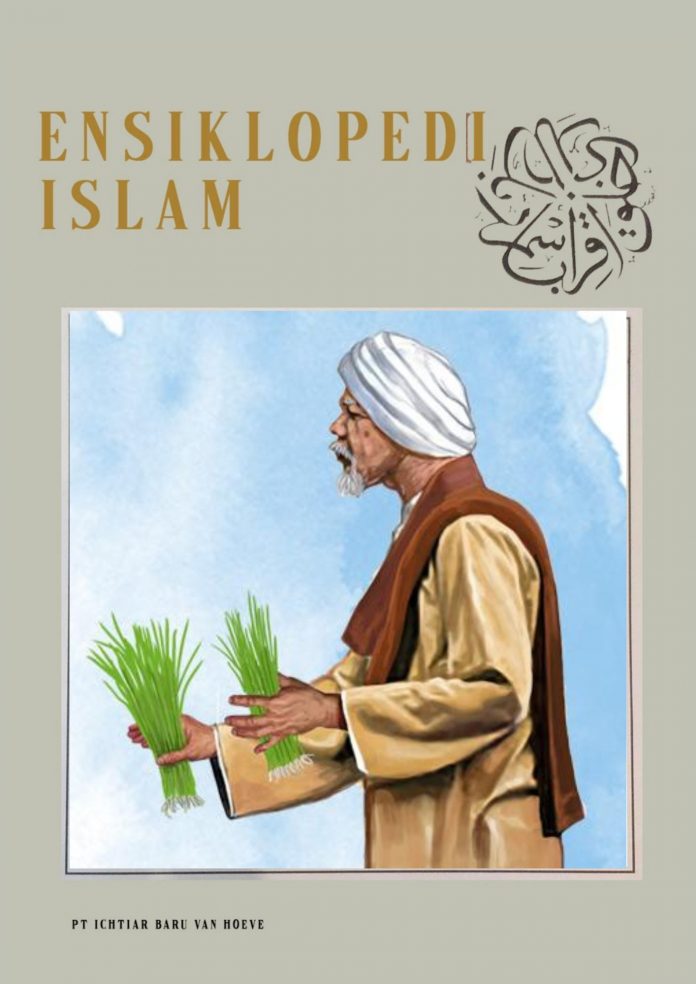Ulama Tarekat Syattariyah yang menyebarkan Islam di Jawa Barat bagian selatan adalah Abdul Muhyi. Ia berasal dari keluarga bangsawan dan dibesarkan di Ampel, Surabaya. Ayahnya, Sembah Lebe Warta Kusumah, adalah keturunan raja Galuh (Pajajaran). Karena ia dipandang wali, makamnya di Pamijahan, Bantarkalong, Tasikmalaya, Jawa Barat dikeramatkan.
Pendidikan agama Islam pertama kali diterima Abdul Muhyi dari ayahnya sendiri dan kemudian dari ulama yang berada di Ampel. Dalam usia 19 tahun, ia berangkat ke Kuala, Aceh, untuk melanjutkan pendidikannya dan berguru kepada Syekh *Abdur Rauf Singkel, seorang ulama sufi dan guru Tarekat Syattariyah.
Syekh Abdur Rauf Singkel adalah ulama Aceh yang berupaya mendamaikan ajaran martabat alam tujuh –yang dikenal di Aceh sebagai paham wahdatul wujud atau wujudiyyah (panteisme dalam Islam)– dengan paham sunah. Meskipun begitu, Syekh Abdur Rauf Singkel tetap menolak paham wujudiyyah yang menganggap adanya penyatuan antara Tuhan dan hamba. Ajaran inilah yang kemudian dibawa Syekh Haji Abdul Muhyi ke Jawa.
Masa studinya di Aceh dihabiskannya dalam tempo 6 tahun (1090 H/1669 M–1096 H/1675 M). Setelah itu, bersama teman seperguruannya ia dibawa gurunya ke Baghdad dan kemudian ke Mekah untuk lebih memperdalam ilmu pengetahuan agama dan menunaikan ibadah haji. Setelah menunaikan ibadah haji, ia kembali ke Ampel, Jawa Timur.
Setelah menikah, ia meninggalkan Ampel dan mulai melakukan pengembaraan ke arah barat bersama istri dan orangtuanya. Mereka kemudian tiba di Darma, termasuk daerah Kuningan, Jawa Barat. Atas permintaan masyarakat muslim setempat, ia menetap di sana selama 7 tahun (1678–1685) untuk mendidik masyarakat dengan ajaran agama Islam.
Setelah itu, ia kembali mengembara dan sampai ke daerah Pameungpeuk, Garut, Jawa Barat. Ia menetap di Pameungpeuk selama setahun (1685–1686) untuk menyebarkan agama Islam di kalangan penduduk yang ketika itu masih menganut agama Hindu.
Pada 1686 ayahnya meninggal dunia dan dimakamkan di kampung Dukuh di tepi Kali Cikaengan. Beberapa hari setelah pemakaman ayahnya, ia melanjutkan pengembaraan hingga ke daerah Batuwangi. Ia bermukim beberapa waktu di sana atas permintaan masyarakat. Setelah itu ia ke Lebaksiuh, tidak jauh dari Batuwangi.
Lagi-lagi, atas permintaan masyarakat ia bermukim di sana selama 4 tahun (1686–1690). Pada masa 4 tahun itu, ia berjasa mengislamkan penduduk yang sebelumnya menganut agama Hindu. Menurut cerita rakyat, keberhasilannya dalam melakukan dakwah Islam terutama karena kekeramatannya yang mampu mengalahkan “aliran hitam”.
Di sini Syekh Haji Abdul Muhyi mendirikan masjid tempat ia memberikan pengajian untuk mendidik para kader yang dapat membantunya menyebarkan agama Islam lebih jauh ke bagian selatan Jawa Barat. Setelah 4 tahun menetap di Lebaksiuh, ia memilih bermukim di gua yang sekarang dikenal sebagai Gua Safar Wadi di Pamijahan, Tasikmalaya, Jawa Barat.
Menurut salah satu tradisi lisan, kehadirannya di Gua Safar Wadi itu adalah atas undangan bupati Sukapura, yang meminta bantuannya untuk menumpas aji-aji hitam Batara Karang di Pamijahan. Di sana terdapat sebuah gua tempat pertapaan orang yang menuntut aji-aji hitam itu. Syekh Haji Abdul Muhyi memenangkan pertarungan melawan orang tersebut hingga ia dapat menguasai gua itu.
Ia menjadikan gua itu tempat pemukiman bagi keluarga dan pengikutnya, di samping tempat memberikan pengajian agama dan mendidik kader dakwah Islam. Gua tersebut sangat sesuai baginya dan para pengikutnya untuk melakukan semadi menurut ajaran Tarekat Syattariyah. Sekarang, gua tersebut banyak diziarahi orang sebagai tempat mendapatkan “berkah”.
Syekh Haji Abdul Muhyi juga bertindak sebagai guru agama Islam bagi keluarga bupati Sukapura, Bupati Wiradadaha IV, R. Subamanggala. Setelah sekian lama bermukim dan mendidik para santrinya di dalam gua, ia dan pengikutnya berangkat menyebarkan agama Islam di kampung Bojong (sekitar 6 km dari gua, sekarang lebih dikenal sebagai kampung Bengkok) sambil sesekali kembali ke Gua Safar Wadi.
Sekitar 2 km dari Bojong, ia mendirikan perkampungan baru yang disebut kampung Safar Wadi. Di kampung itu ia mendirikan masjid (sekarang menjadi kompleks Masjid Agung Pamijahan) sebagai tempat beribadah dan pusat pendidikan Islam. Di samping masjid ia mendirikan rumah tinggalnya. Sementara itu, para pengikutnya aktif menyebarkan agama Islam di daerah Jawa Barat bagian selatan. Melalui para pengikutnya, namanya terkenal ke berbagai penjuru Jawa Barat.
Menurut tradisi lisan, Syekh Maulana Mansur berulang kali datang ke Pamijahan untuk berdialog dengan Syekh Haji Abdul Muhyi. Syekh Maulana Mansur adalah putra Sultan Abdul Fattah Tirtayasa dari Kesultanan Banten. Sultan Tirtayasa sendiri adalah keturunan Maulana Hasanuddin, sultan pertama Kesultanan Banten yang juga putra Syarif Hidayatullah atau Sunan Gunung Jati, salah seorang Wali Songo.
Berita tentang ketinggian ilmunya itu sampai juga ke telinga sultan Mataram. Sultan kemudian mengundang Syekh Haji Abdul Muhyi untuk menjadi guru bagi putra-putrinya di istana Mataram. Sultan Mataram Paku Buwono II (1727–1749) ketika itu bahkan menjanjikan akan memberi piagam yang memerdekakan daerah Pamijahan dan menjadikannya daerah “perdikan”, daerah yang dibebaskan dari pembayaran pajak.
Undangan sultan Mataram itu tidak sempat dilaksanakannya, karena 1151 H/1730 M Syekh Haji Abdul Muhyi meninggal dunia karena sakit di Pamijahan. Berdasarkan keputusan sultan Mataram itulah, oleh pemerintah kolonial Hindia Belanda, melalui keputusan residen Priangan, Pamijahan sejak 1899 dijadikan daerah ”pasidkah”, daerah yang dikuasai secara turun-temurun dan bebas memungut zakat, pajak, dan pungutan lain untuk keperluan daerah itu sendiri.
Makam Syekh Haji Abdul Muhyi yang terletak di Pamijahan diurus dan dikuasai keturunannya. Makamnya itu ramai diziarahi orang sampai sekarang karena dikeramatkan. Sampai saat ini Desa Pamijahan dipimpin oleh seorang khalifah, jabatan yang diwariskan secara turun-temurun, yang juga merangkap sebagai juru kunci makam dan mendapat penghasilan sedekah dari para peziarah.
Karya tulis Syekh Haji Abdul Muhyi yang asli tidak ditemukan lagi. Akan tetapi ajarannya disalin oleh muridnya, antara lain putra sulungnya sendiri, Syekh Haji Muhyiddin, yang menjadi tokoh Tarekat Syattariyah sepeninggal ayahnya. Syekh Haji Muhyiddin menikah dengan seorang putri Cirebon dan lama menetap di Cirebon.
Ajaran Syekh Haji Abdul Muhyi versi Syekh Haji Muhyiddin ini ditulis dengan huruf pegon (Arab Jawi) dengan menggunakan bahasa Jawa (baru) pesisir. Naskah versi Syekh Haji Muhyiddin itu berjudul Martabat Kang Pitutu (Martabat Alam Tujuh) dan sekarang terdapat di Museum di Belanda, dengan nomor katalog LOr. 7465, LOr. 7527, dan LOr. 7705.
Ajaran “martabat alam tujuh” ini berawal dari ajaran tasawuf wahdatul wujud (kesatuan wujud) yang dikembangkan Ibnu Arabi. Tidak begitu jelas kapan ajaran ini pertama kali masuk ke Indonesia. Yang jelas, sebelum Syekh Haji Abdul Muhyi, sudah ada beberapa ulama sufi Indonesia yang menulis ajaran ini, seperti Hamzah Fansuri, Syamsuddin as-Sumatrani (tokoh sufi, w. 1630), dan Abdul Rauf Singkel, dengan variasi masing-masing. Oleh karena itu sangat lemah untuk mengatakan bahwa karya Syekh Haji Abdul Muhyi yang berjudul Martabat Kang Pitutu ini sebagai karya orisinilnya, tetapi besar kemungkinan merupakan saduran dari karya yang sudah terdapat sebelumnya dengan penafsiran tertentu darinya.
Menurut ajaran “martabat alam tujuh”, seperti yang tertuang dalam Martabat Kang Pitutu, wujud yang hakiki mempunyai tujuh martabat, yaitu: (1) ahadiyyah, hakikat sejati Allah SWT; (2) wahdah, hakikat Muhammad SAW; (3) wahidiyyah, hakikat Adam AS; (4) ‘alam arwah, hakikat nyawa; (5) ‘alam misal, hakikat segala bentuk; (6) ‘alam ajsam, hakikat tubuh; dan (7) ‘alam insan, hakikat manusia. Kesemuanya bermuara pada yang satu, yaitu ahadiyyah, Allah SWT.
Dalam menjelaskan ketujuh martabat ini, Syekh Haji Abdul Muhyi pertama-tama menggarisbawahi perbedaan antara Tuhan dan hamba, agar –sesuai dengan ajaran Syekh Abdul Rauf Singkel– orang tidak terjebak pada identiknya alam dengan Tuhan. Ia mengatakan bahwa wujud Tuhan itu qadIm (azali dan abadi), sementara keadaan hamba adalah muhdas (baru).
Dari tujuh martabat itu, yang qadam itu meliputi martabat ahadiyyah, wahdah, dan wahidiyyah, semuanya merupakan martabat “keesaan” Allah SWT yang tersembunyi dari pengetahuan manusia. Inilah yang disebut sebagai wujudullah. Empat martabat lainnya termasuk dalam apa yang disebut muhdas, yaitu martabat yang serba mungkin, yang baru terwujud setelah Allah SWT memfirmankan “kun” (jadilah).
Selanjutnya, melalui martabat tujuh itu Syekh Haji Abdul Muhyi menjelaskan konsep insan kamil (manusia sempurna). Konsep ini merupakan tujuan pencapaian aktivitas sufi yang hanya bisa diraih dengan penyempurnaan martabat manusia agar sedekat-dekatnya “mirip” dengan Allah SWT. Melalui usaha Syekh Haji Muhyiddin, ajaran martabat tujuh yang dikembangkan Syekh Haji Abdul Muhyi tersebar luas di Jawa pada abad ke-18.
Daftar Pustaka
Abdullah, Hawash. Perkembangan Ilmu Tasawuf dan Tokoh-Tokohnya di Nusantara. Surabaya: al-Ikhlas, 1980.
Ali, Yunasril. Pengantar Ilmu Tasawuf. Jakarta: Pedoman Ilmu Jaya, 1986.
Apap, R Abdullah bin R. Haji Abdullah Miftah. Sejarah Pamijahan; Kisah Perjuangan Syekh Haji Abdul Muhyi Mengembangkan Agama Islam di Sekitar Jabar. Pamijahan: t.p., t.t.
Dhofier, Zamakhsyari. Tradisi Pesantren Suatu Studi Tentang Pandangan Hidup Kyai. Jakarta: LP3ES, 1982.
Khaerussalam, A.A. Sejarah Perjuangan Syekh Abdul Muhyi Waliyyullah. Pamijahan: Usaha Muda, 1994.
Mahmud, Abdul Qadir. al-Falsafah al-Falsafah as-Sufiyyah fi al-Islam. Cairo: Dar al-Fikr al-‘Arabi, 1974.
Santrie, Aliefya M. “Martabat (Alam) Tujuh, Suatu Naskah Mistik Islam dari Desa Karang, Pamijahan,” Warisan Intelektual Islam Indonesia: Telaah atas Karya-Karya Klasik. Bandung: Mizan, 1990.
Badri Yatim