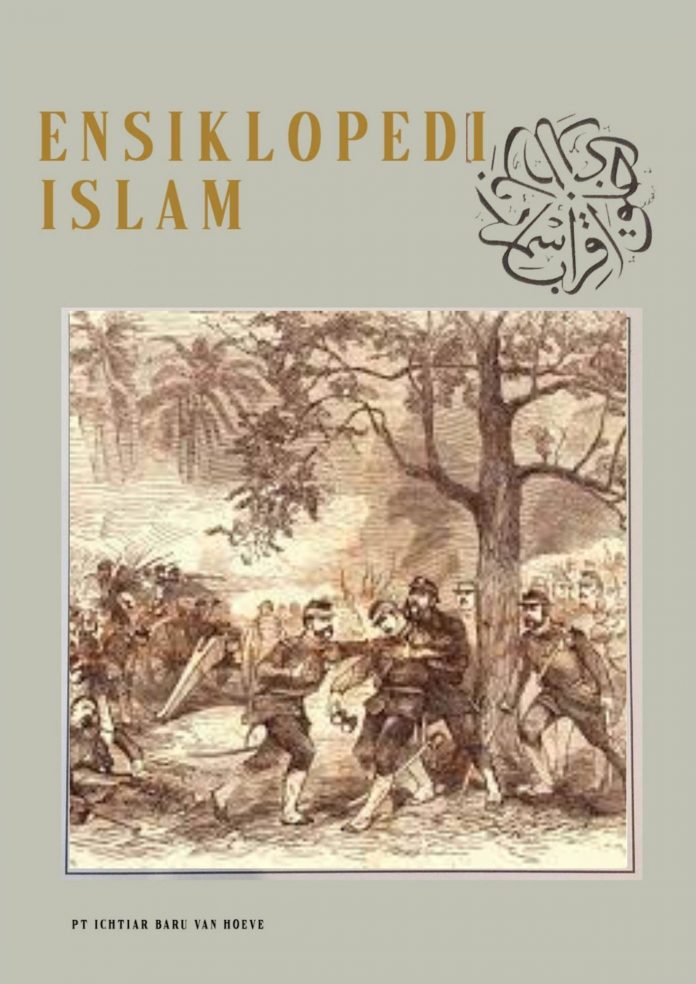Perlawanan rakyat Aceh terhadap Belanda pada akhir abad ke-19 hingga awal abad ke-20 disebut Perang Aceh. Bagi Aceh, ini merupakan perang agama (sabil). Perang berawal ketika Belanda berusaha menguasai Aceh sebagai penghasil lada dan baru berakhir pada 1912. Perang Aceh melahirkan sejumlah pahlawan seperti Teungku Tjik Di Tiro, Teuku Umar, Tjoet Njak Dien, dan Tjoet Meutia.
Tidak seperti kebanyakan daerah Nusantara lain, Belanda membutuhkan waktu panjang untuk bisa menaklukkan Aceh. Hal ini karena jauh sebelum Belanda menguasai Aceh, Aceh merupakan salah satu kerajaan besar Islam pada abad ke-17, terutama pada masa pemerintahan Sultan Iskandar Muda (1607–1636).
Pada masa itu, Aceh tidak saja mengalami kemajuan di bidang pemikiran, ekonomi, dan dakwah Islam, tetapi juga di bidang militer. Semua itu menjadikan Kesultanan Aceh salah satu kerajaan yang tangguh. Sepeninggal Sultan Iskandar Muda, Aceh mulai mengalami kemuduran.
Usaha untuk mengembalikan wibawa Kesultanan Aceh dilakukan sultan yang memerintah Aceh pada abad ke-19, yakni Sultan Alauddin Muhammad Daud Syah. Tetapi, ia menghadapi persoalan eksternal yang tidak ringan. Pada masa pemerintahannya, ditandatangani Traktat London antara Inggris dan Belanda pada 1824 tentang pembagian wilayah jajahan.
Perjanjian tersebut antara lain menyatakan bahwa Belanda tidak boleh mengganggu kedaulatan Aceh. Pada kenyataannya, Belanda tetap berusaha memperluas wilayah jajahannya, sampai ke beberapa wilayah pinggiran Aceh dan Siak (sekarang Propinsi Riau Daratan).
Cara yang ditempuh Belanda dalam memperluas wilayah kekuasaannya tentu saja mengkhawatirkan Kesultanan Aceh, apalagi setelah perjanjian antara Inggris dan Belanda pada 2 November 1871, yang isinya memberi kebebasan bagi Belanda untuk memperluas wilayah jajahannya, termasuk Aceh.
Hasrat Belanda menguasai Aceh sangat besar karena posisi sentral Aceh, terutama setelah dibuka Terusan Suez pada 1869. Setelah Terusan Suez dibuka, Selat Malaka menjadi ramai, sementara Aceh menjadi pintu gerbang menuju selat tersebut.
Melihat gelagat yang tidak menguntungkan tersebut, sultan Aceh berusaha meminta bantuan dari Turki, Amerika Serikat, dan Italia. Sementara itu, pada akhir Agustus 1872, utusan Belanda datang menghadap sultan. Utusan itu membawa surat dari pemerintah Hindia Belanda agar Aceh mau mengakui kedaulatan Belanda atasnya. Permintaan ini ditolak sultan. Utusan kedua datang lagi pada Maret 1873 dengan misi yang sama. Karena tawaran tersebut ditolak, akhirnya Belanda memaklumkan perang dengan Aceh pada 26 Maret 1873.
Dengan maklumat perang di atas, mulailah perang rakyat Aceh melawan imperialisme Belanda. Jauh sebelum perang dimulai, rakyat Aceh sebenarnya sudah mempersiapkan diri. Sekitar 3.000 pejuang Aceh bersiaga penuh di sepanjang pantai, sementara sekitar 4.000 pejuang lain mempertahankan istana kesultanan. Selain itu, Aceh berhasil memasukkan 5.000 peti mesiu dan 1.394 peti senapan dari Penang.
Pada 5 April 1873, pasukan Belanda di bawah pimpinan Mayor Jenderal J.H.R. Kohler sebanyak lebih dari 3.000 orang mendarat di perairan Aceh. Pasukan ini langsung disambut pejuang Aceh yang mempertahankan wilayah pantai. Karena kekuatan Belanda lebih besar, pasukan Aceh terpaksa mundur dari daerah pantai.
Setelah wilayah pantai jatuh ke tangan Belanda, pejuang Aceh memperkuat pertahanan mereka di Masjid Raya Baiturrahman. Di masjid ini terjadi peperangan sengit antara pasukan Aceh dan Belanda. Pertahanan pejuang Aceh di masjid ini demikian kuat sehingga dapat memukul mundur pasukan Belanda.
Tetapi, Belanda datang kembali dengan pasukan yang lebih banyak mengepung masjid ini dari berbagai penjuru, sehingga pertahanan pasukan Aceh dapat dipatahkan. Masjid ini dapat dikuasai Belanda pada 14 April 1873. Dalam pertempuran di Masjid Raya Baiturrahman, komandan pasukan Belanda, Mayor Jenderal J.H.R. Kohler, tewas.
Setelah Masjid Raya Baiturrahman jatuh ke tangan Belanda, pertahanan rakyat Aceh dipusatkan di istana Sultan Mahmud Syah. Pada 16 April 1873, pasukan Belanda yang kini bermarkas di Masjid Raya Baiturrahman bergerak menuju istana tersebut sebagai sasaran berikutnya. Kedatangan serdadu Belanda segera disambut pasukan Aceh yang mempertahankan istana Sultan Mahmud Syah sebagai pertahanan terakhir mereka.
Pasukan Aceh di istana cukup kuat sehingga dapat memukul mundur pasukan Belanda. Pasukan Aceh juga berhasil merebut kembali Masjid Raya Baiturrahman dari Belanda dan memaksa mereka kembali ke daerah pantai. Pasukan ini akhirnya meninggalkan Aceh pada 29 April 1873. Serangan pertama Belanda terhadap Aceh yang berlangsung selama 24 hari ini gagal menaklukkan Aceh.
Serangan kedua Belanda dimulai pada 9 Desember 1873. Pasukan diterjunkan di Kuala Lue dekat Gigieng, Aceh Besar, di bawah pimpinan Letnan Jenderal J. van Swieten. Jauh sebelum Belanda melancarkan serangan, kapal Belanda sudah memblokade Aceh guna menghindari masuknya bala tentara bantuan dari luar ke Aceh.
Di Gigieng, pasukan Belanda disambut dengan perlawanan sengit oleh pasukan Aceh. Namun karena pasukan Belanda begitu besar, pasukan Aceh terpaksa mundur guna memperkuat pertahanan di istana Sultan Mahmud Syah yang menjadi target utama serangan Belanda.
Sebelum menyerang istana Sultan Mahmud Syah, yang menjadi simbol kekuatan Aceh, Belanda pertama-tama merebut Masjid Raya Baiturrahman, lalu menjadikannya benteng pertahanan. Kemudian, pasukan Belanda menyerang istana Sultan Mahmud Syah dengan mengepungnya dari berbagai penjuru.
Setelah bertempur selama kurang lebih 2 minggu, pada 24 Januari 1874 akhirnya istana Sultan Mahmud Syah dapat dikuasai Belanda. Namun, Belanda gagal menangkap Sultan, karena Sultan beserta keluarganya telah mengungsi ke Leunbata beberapa hari sebelum istana jatuh ke tangan Belanda.
Di tempat ini Sultan membangun pertahanan baru bersama Panglima Polem dan lainnya guna melanjutkan perlawanan terhadap Belanda. Hanya saja, tidak lama setelah itu Sultan meninggal dunia (28 Januari 1874) karena terjangkit wabah kolera. Sebagai penggantinya, para panglima perang Aceh sepakat untuk memilih dan mengangkat putra sultan, Muhammad Daud Syah. Karena sultan masih di bawah umur, sultan dibantu Dewan Mangkubumi.
Dengan dikuasainya istana kesultanan, Belanda menduga bahwa rakyat Aceh sudah menyerah. Dugaan itu tercermin pada proklamasi Jenderal van Swieten yang menyatakan bahwa Aceh sudah takluk. Dugaan Belanda tersebut ternyata salah, karena perlawanan rakyat Aceh tidak pernah padam.
Ulama memegang peran kunci dalam Perang Aceh, mereka tidak saja berperan sebagai panglima perang, tetapi juga sebagai mujahid melalui khotbah yang berisi kisah perang, seperti Hikayat Perang Sabil, Hikayat Perang Gompeuni, dan Syair Perang Atjeh. Di bawah komando panglima perang mereka masing-masing, rakyat Aceh terus mengadakan perlawanan dengan taktik gerilya.
Taktik perang ini menyulitkan Belanda, sehingga pengganti Jenderal van Swieten, yakni Jenderal Pel, mengubah taktik perangnya dengan membangun beberapa pos di beberapa tempat sebagai garis pembendung (afsluitings linie).
Perjuangan rakyat Aceh mendapat angin segar dengan kembalinya Habib Abdurrahman dari Turki pada 1877, yang sebelumnya diutus Sultan Aceh ke Turki untuk meminta bantuan. Segera setelah kembali ke Aceh, Habib Abdurrahman mengadakan perundingan dengan beberapa panglima perang guna merancang strategi perang.
Akhirnya perlawanan rakyat Aceh berkobar di beberapa wilayah. Habib Abdurrahman bertugas mengacaukan pertahanan Belanda di pos-pos pembendung di atas dan wilayah lain seperti Blang Ue, Peukan Badak, dan Bukit Sirun. Sementara itu, Teungku Tjik Di Tiro memimpin perjuangan di wilayah Gigieng dan Raja Samalanga, Pidie.
Di Aceh Barat, perlawanan terhadap Belanda dipimpin Teuku Umar yang dibantu istrinya, Tjoet Njak Dien. Ketika Sultan Muhammad Daud Syah dewasa, pada 1884 ia juga turun langsung ke medan perang memimpin perlawanan terhadap Belanda.
Kewalahan menghadapi perlawanan rakyat Aceh, Belanda mengubah taktik perangnya. Salah satunya adalah mengirim seorang ahli tentang Islam, Snouck Hurgronje (1857–1936), yang bertugas menyelidiki akar kekuatan perlawanan Rakyat Aceh. Hurgronje berkesimpulan bahwa salah satu faktor yang menyuplai semangat rakyat Aceh untuk melawan Belanda adalah agama.
Berkat saran Snouck Hurgronje, Belanda berhasil mengikat kerjasama dengan sejumlah uluebalang. Hal tersebut berhasil memecah belah antara ulama dan uluebalang. Dengan segera perlawanan rakyat Aceh dapat dipatahkan. Akhirnya Teuku Umar tewas dan Panglima Polem menyerah setelah keluarganya ditangkap.
Pada 1904, hampir seluruh perlawanan rakyat Aceh telah dapat dipatahkan. Belanda dapat menguasai Aceh secara keseluruhan dan sultan terakhir, Muhammad Daud Syah, diasingkan ke Ambon pada 1907.
Daftar Pustaka
Alfian, Ibrahim. Perang di Jalan Allah. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1987.
Auni, Luthfi. “The Decline of Islamic Empire of Aceh (1641–1699),” Tesis Master di McGill University, April, 1993.
Ismuha. “Ulama Aceh dalam Perspektif Sejarah,” Agama dan Perubahan Sosial, ed. Taufik Abdullah. Jakarta: Rajawali Pers, 1983.
Yatim, Badri. Sejarah Peradaban Islam. Jakarta: Rajawali Pers, 1993.
Din Wahid